Liburan semester itu Mona memutuskan untuk menerima ajakan Florence mengunjungi tantenya di luar kota. Setidaknya itu bisa jadi cara jitu untuk menenangkan diri dan mengurangi segala kepenatan.
“Gue nggak tau kalo lo ternyata punya kakak laki-laki,” ujar Mona memecah kebisuan. Kaget juga saat Florence tadi menjemputnya bersama cowok cakep banget yang diperkenalkan sebagai Charles, “Gue kira kakak lo tuh ya Kak Diva.”
Florence yang sedang baca majalah senyum-senyum sendiri, “MB,” celetuknya jahil.
“MB? Apaan tuh?”
“Emang bener,” sahut Florence cekikikan dan sebagai balasannya sebuah jitakan kecil mengenai ubun-ubun cewek itu, “Kakak gue ya cuma Kak Diva. Kalo Kak Charles sih kakak sepupu. Kebetulan dia lagi main so Mom langsung nyuruh dia buat nganterin kita ke stasiun.”
“Oh,” Mona manggut-manggut, “Tau nggak, dari dulu gue pingin banget punya kakak.”
“Lho kok?” Florence menengok dan menatap sahabatnya—heran, “Bukannya lebih enak jadi anak tunggal?”
“Iya sih. Gue jadi nggak berebut apapun sama orang lain kayak adik kakak pada umumnya,” renung Mona membasahi bibir, mengingat kesehariannya, “Tapi gue lebih sering kesepian. Bokap sibuk kerja di kantor dan nyokap asyik banget sama butiknya. Coba kalo tiap hari lo ke rumah gue.”
“Your wish,” Florence terkekeh dan kembali memusatkan perhatiannya pada majalah remaja itu.
Mona terdiam. Ia menyandarkan kepalanya dalam sebuah helaan nafas. Pandangannya beralih keluar jendela. Langit tampak jingga. Hatinya miris melihat bola api merah yang perlahan bergerak mendekati garis cakrawala. Cahaya keemasan masih berpendar indah di atas kemilau laut biru yang bergelombang. Senja!
Mona memejamkan mata. Senja di pantai! Entah kenapa rasanya semua itu tak asing lagi baginya. Dan bayangan itu melintas di otaknya.
Ia tengah duduk di bibir pantai ketika cowok itu menghampirinya. Sesekali angin berdesing atau sekedar mengacak-acak rambut panjangnya. Sementara camar nan jauh di sana memekik dan terus berteriak nyaring bersama kawanannya.
“Sebelumnya gue nggak pernah lihat sunset,” kata Mona. Suara debur ombak yang memecah pantai membuatnya demikian rileks. Bahkan ia bisa mencium bau air laut yang asin, “Indah banget ya,” dan ia pun menoleh ke arah cowok itu.
“Gue juga nggak bakal lupa saat-saat ini,” cowok itu terus memandang ke arah lautan, “Mon, boleh nggak gue minta satu hal?”
“Apa?”
Cowok itu berpaling dan menelengkan kepalanya hingga kesenduannya mampu menembus mata Mona yang kelam, “Jangan pernah tinggalin gue, please,” ucapnya lirih, “Gue sayang lo, Mon.”
Mona trenyuh. Untuk pertama kali ia merasakan hatinya bergetar begitu kerasnya, “Tapi kita kan baru 13 tahun. Mana boleh kita pacaran.”
“You are my first love,” ujar cowok itu dalam, “Mungkin lo bisa bohongin gue tapi lo nggak akan bisa bohongin diri lo sendiri. Lo juga sayang gue kan, Mon?”
Mona membisu.
“Mon?”
“Yes, I do,” gumam Mona dengan suara parau.
“Berarti hari ini kita jadian.”
Mona tersentak dan bangkit dari duduknya dengan terengah-engah.
“Mon, ada apa?” seru Florence terkejut.
“Gue—” sengal Mona menyeka keringat dingin di pelipisnya “Cowok itu—pantai—”
“Udah, lo duduk aja dulu,” Florence berbisik di telinganya, “Malu diliatin orang.”
Masih dengan dada kembang kempis Mona memandang berkeliling dan ia baru sadar puluhan pasang mata di gerbong itu terarah padanya, penuh rasa ingin tahu.
“Duduk sini,” bimbing Florence menuju kursi mereka sedangkan Mona masih terlihat limbung seperti orang yang terhipnotis, “Sebenernya ada apa sih, Mon?” tanya Florence ketika keadaan sahabatnya sudah mulai tenang.
“Gue inget siapa cowok itu,” ucap Mona datar. Tatapannya kosong seolah dia berada di dunia lain, “Dia pacar gue. Cinta pertama gue.”
Florence terperangah. Selama beberapa detik ia tak sanggup bicara, “Pacar lo?” hanya itu yang bisa keluar dari mulutnya.
Mona mengangguk yakin, “Di pantai, kita liat sunset bareng. Dia bilang dia sayang gue dan gue juga punya perasaan yang sama. Kita jadian. Waktu itu kita baru tiga belas tahun—” dan ia tertegun menyadari sesuatu, “Tiga belas tahun?”
“Ada apa?” dahi Florence semakin berkerut.
“Sekarang umur gue 18 tahun dan kecelakaan itu terjadi lima tahun yang lalu. Lo paham kan maksud gue? Itu artinya semua ini nyata. Dan cowok itu bukan khayalan gue.”
“Dengan kata lain ingatan lo bener pulih,” komentar Florence mulai paham, “Terus siapa nama cowok lo itu?”
“Namanya—siapa ya namanya?” Mona pun mendesah kecewa, “Itu dia—gue juga belum tau.”
“Udah nggak papa,” Florence menepuk-nepuk punggung Mona, berusaha menyemangati, “May be next time. Tapi yang jelas, lo udah mengalami suatu kemajuan yang besar. Suatu hari pasti ada yang bisa lo inget lagi.”
“Ya,” sahut Mona suram.
Kereta terus melaju dan laut itu masih berkilauan. Warnanya yang semula biru kini oranye seiring matahari yang terbenam. Cahayanya meredup dalam bias ungu lembayung, meninggalkan kesan yang amat dramatis. Senja di pantai itu!
***
Mona dan Florence turun di stasiun tujuan kala hari telah benar-benar gelap. Arloji mereka menunjukan pukul 21.00 dan biasanya jam segini Mona sudah mulai mengantuk.
“Habis ini kita kemana lagi nih, Flo?” tanya Mona membenarkan letak ranselnya yang super berat.
“Ya nunggu,” sahut Florence berhenti saat terjebak antrian kecil untuk bisa keluar dari gerbong itu, “Tante Linda janji mau jemput kita di sini. Yang penting lo jangan jauh-jauh dari gue. Lo kan nggak tau daerah ini. Bisa-bisa lo nyasar. Gue nggak tanggung jawab lho.”
“Lagian ngapain juga gue pisah dari lo,” cibir Mona manyun, “Kan lo yang ngajak gue ke sini. Jadi lo bosnya,” dan ia tertawa geli melihat Florence repot menyeret kopernya yang sedikit kebesaran untuk ukuran seorang Florence yang mungil.
Mereka menyusuri peron yang panjang dan hitam. Di sisi mereka tampak berjejer kios yang tak henti-hentinya menawarkan barang dagangan. Dan Florence mendudukan dirinya di sebuah kursi kayu panjang yang jadul banget, “Capek juga ya.”
Sebagai jawabannya Mona hanya mengangguk. Stasiun itu cukup lengang dengan penerangan lampu-lampu boghlam yang tak lebih dari 60 Watt. Agak remang memang, tapi setidaknya cukup memadai.
“Tante Linda itu adik Dad. Gue lebih deket sama dia daripada adik Mom yang di Paris itu. Mungkin karena jarang ketemu. Tante Linda nikah sama Om Billy setahun yang lalu dan beli satu hektar tambak di sini—” Florence masih bercerita soal usaha wiraswasta milik tantenya. Namun Mona tidak lagi mendengarkan karena perhatiannya kini terpusat pada sosok cowok tinggi putih yang berjalan cepat menuju tanda exit. Entah kenapa rasanya Mona pernah melihat laki-laki itu sebelumnya.
“Mon, lo dengerin gue nggak sih?” tandas Florence kesal.
Mona sama sekali tidak menyahut. Ia bangkit dan bergegas lari menyusul sosok yang baru saja dilihatnya. Cowok itu! Cowok yang sama dalam mimpinya.
“MONA, LO MAU KEMANA?” Florence memekik kaget. Ia menggeram dan mengejar sobatnya sebelum kehilangan jejak, “Nih anak cari perkara aja. Udah dibilangin jangan jauh-jauh dari gue malah pergi seenaknya sendiri nggak jelas gitu,” makinya ngos-ngosan.
Mona terus mengayunkan langkah lebarnya sampai di pintu keluar. Sepi! Ia memandang berkeliling, sangat berharap matanya menangkap bayangan cowok itu sekalipun. Namun sia-sia. Dan ia tersentak ketika sesuatu menyambar tangannya keras-keras.
“Lo apa-apaan sih, Mon?” teriak Florence mencengkram pergelangan tangan Mona.
“Gue—tadi gue liat dia di sini—” gagap Mona dengan tersengal.
“Dia siapa?” tuntut Florence tak sedikitpun menutupi kemarahannya.
“Cowok itu!”
“Cowok di mimpi lo?” hardik Florence pedas. Menurutnya Mona sekarang sudah sangat keterlaluan. Kekonyolan ini sudah tidak lucu lagi.
“Iya.”
Florence mengernyit dengan tatapan prihatin, “Mon, gue jadi takut. Kayaknya tadi lo cuma berhalusinasi deh.”
“Nggak! Gue yakin banget. Cowok itu tadi ada di sini,” seru Mona keras kepala dan kabut hangat itu mulai menghalangi pandangannya, “Cowok itu tinggi, baby face banget dan dia pakai kameja merah.”
“Sori, gue nggak liat ada cowok kayak yang lo deskripsiin itu,” tukas Florence menggeleng lemah. “Tapi gue nggak bohong, Flo,” jerit Mona berurai air mata, “Gue nggak bohong!”
“Gue ngerti ini berat banget buat lo,” desah Florence merangkul sahabatnya, “Mungkin aja ingatan lo mulai pulih. Tapi gue rasa lo udah terobsesi keinginan lo untuk cari tau masa lalu lo yang hilang itu.”
Mona menghapus air matanya, “Maksud lo, apa yang tadi gue liat cuma imajinasi gue?” sahutnya terisak.
Florence mengiyakan dalam anggukan kecil, “Lo mesti percaya takdir, Mon. Kalo lo emang berjodoh sama tuh cowok, kalian pasti ketemu lagi.”
Sejenak Mona lega mendengar penjelasan itu. Selalu saja Florence yang bisa memahami perasaannya. Seandainya Papa dan Mama bisa sebijak Florence dan tidak menyembunyikan kenyataan ini, tentu Mona tidak akan demikian resah. Tapi Mona sadar kalau jodoh takkan lari kemana. Dan ia berdoa agar dipertemukan dengan cowok itu.
Bersambung ...
Selasa, 03 Februari 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)




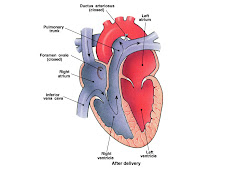











.jpg)
















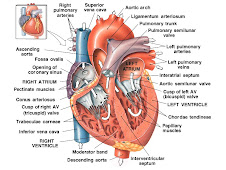






.jpg)













Tidak ada komentar:
Posting Komentar