GWEN
Arloji di tanganku telah menunjukkan pukul 15 lewat sepuluh. Aku masih setia menjejakan kaki di sekitar gerbang sekolah. Tempat itu hampir sepi. Sudah bisa dipastikan kegiatan belajar mengajar telah selesai lebih dari sejam yang lalu. Dan aku bengong di sini kayak orang dungu demi menunggu seorang cowok brengsek yang akhir-akhir ini membuatku demikian resah. Siapa lagi kalau bukan Dika, kekasihku.
Berkali-kali aku menjulurkan leher berharap melihat sosoknya yang tegap muncul dengan Ninja biru kesayangannya. Perlahan rasa sesal mulai menggerogotiku. Harusnya tadi aku terima saja tawaran Vivi untuk pulang bareng.
“Bener nih lo nggak mau ikut?” tanya teman sebangkuku untuk kesekian kalinya.
“He-em, Dika janji mau jemput gue.
Dika adalah anak tenik sipil di salah satu universitas swasta nan elite di
“Tapi nggak papa nih lo ditinggal sendirian?”
“Ya, nggak usah khawatir gitu,” ujarku meyakinkan.
Mata mungil Vivi mengamatiku dengan cemas, “Ooo ya udah deh kalo itu mau lo. Lagian gue juga nggak bisa maksa lo,” akhirnya cewek itu menyerah dan melambaikan tangannya saat Sirion itu perlahan melaju di jalanan yang cukup lengan.
Sekarang aku hanya bisa mendesah antara kesal dan tak sabar untuk bertemu Dika. Alone! Kakiku sudah terasa pegal dan aku tak berniat beranjak sedikit pun. Matahari sore kian memanggangku dan gerah rasanya berhadapan dengan cahaya silaunya yang seakan persis di depan wajahku. Debu dan keringat yang semakin bercucuran tak dapat menahanku untuk tidak mengeluh. Penantian ini mendadak terasa sangat menjengkelkan. Kalau terlambat beberapa menit masih bisa aku maklumi, tapi ini sudah hampir 2 jam. Nah lo, siapa yang nggak kesel coba?
Aku tersentak kaget merasa getar ponsel yang seperti menggelitiku. Sebuah nama tertera di layar ‘Dika memanggil’
“Halo, Say!” seruku antusias tapi rasa senangku sirna begitu mendengar apa yang dikatakan Dika berikutnya.
“Ris, sori ya, hari ini gue nggak bisa jemput lo.”
“Tapi lo kan janji mau ngajak gue ke butik nyokap lo,” protesku tak mau kalah.
“Iya gue ngerti. tapi gue bener-bener nggak bisa.”
Aku menggigit bibir bawahku yang bergetar, “Terus kenapa lo nggak kasih tau gue dari tadi? Kalo tau gini, gue nggak bakal capek-capek nungguin lo,” seruku naik pitam.
“Gue lupa, Ris.”
“Lupa?” pekikku mengertakan gigi, “Lo bilang lupa?”
“Gue tau gue salah, tapi jangan kayak orang histeris gitu dong.”
“Eh, lo tau nggak, gue berdiri di sini 2 jam, panas terpanggang sampe gue mau pingsan dan lo seenaknya ngebatalin janji. Lo keterlaluan banget ya,” geramku meledak marah hingga tanpa sadar kabut panas menghalangi pandanganku.
“Sayang, gue kan udah minta maaf. Tolong lo ngertiin gue,” aku mendengar ada nada mununtut dari suara Dika.
“Lo tuh yang nggak bisa ngertiin gue,” kataku setengah berteriak, “Memangnya apa sih urusan yang lebih penting dari gue sampe lo ngebatalin janji tanpa nelpon dulu ke gue?”
“Masalahnya Gwen sakit, jadi gue mesti bawa dia ke dokter.”
Aku ternganga, nyaris tak percaya kata-kata yang singgah di telingaku, “Gwen?”
“Ya Ris, gue sayang banget sama dia jadi gue nggak mau dia kenapa-napa—” selebihnya aku mematikan Hp ku. Aku tak mau mendengar lagi apapun yang dikatakan Dika.
Gwen lagi Gwen lagi! Aku nggak bisa ngerti jalan pikiran Dika dan mungkin aku nggak akan pernah bisa mengerti. Siapa sebenarnya Gwen itu? Dilihat dari namanya pasti dia sangat cantik. Dan tadi Dika bilang dia sangat menyayangi Gwen. Mungkinkah Dika berpaling ke cewek lain? Ini sungguh menyakitkan. Dadaku begitu sesak dan tangis itu akhirnya pecah.
Yang ku tahu selama ini hubunganku dengan Dika baik-baik saja, tak pernah ada masalah. Teman-temanku maupun Dika banyak yang iri dengan kelanggengan kami dan cinta ini telah bertahan lebih dari setahun. Namun semuanya berubah sejak kehadiran sosok bernama Gwen yang tidak ku kenal sama sekali. Perhatian Dika terhadapku jauh berkurang. Paling tidak aku yang merasa seperti itu. Sementara Dika selalu menganggap everything’s fine.
Aku ingat betul di ulang tahun Dika yang ke 19 aku bersusah payah menyiapkan dinner seromantis mungkin di sebuah kafe kenamaan. Hanya ada aku dan Dika, itulah yang kuinginkan. Awalnya segala sesuatu berjalan sempurna, tapi kebahagiaan itu lenyap saat Dika menerima panggilan dari airport.
“Aduh, Sayang, gue harus jemput Tante Linda dan Gwen nih. Kenalan Mama dan kayaknya mereka baru tiba dari Aussie,” katanya waktu itu dan dia beranjak pergi sebelum aku sempat membuka mulut.
Hari itu menjadi saat terburuk dalam hidupku. Aku sangat sedih dan kecewa. Menurutku Dika tak lagi menghargai apapun yang kulakukan untuknya. Dan sepanjang malam aku duduk merana seorang diri sampai kafe itu tutup.
Dan di lain kesempatan, setiap kali aku bertemu Dika, yang selalu jadi bahan pembicaraan tak lain dan tak bukan adalah Gwen!
“Makin hari Gwen tambah imut lho.”
Aku mendengus, “Lo suka ya sama dia?” tanyaku ketus. Meski tak mau mengakui, ada rasa nyeri menyusup di kalbu.
“Ya jelas dong, siapa sih yang nggak suka sama Gwen. Dia itu luar biasa.”
“Terus kenapa lo milih gue, pacarin aja si Gwen itu,” sungutku semakin manyun.
Dika tertawa keras seolah ada yang lucu dengan ucapanku, “Ya nggak gitu dong, Risty.”
“Habisnya lo muji Gwen terus sih.”
“Cemburu ya?” ledek Dika dan dia terbahak-bahak.
Begitu selalu. Dika tak pernah menjelaskan siapa Gwen yang dimaksud itu. Aku merasa ada sesuatu yang Dika sembunyikan. Dan aku sungguh tak suka main kucing-kucingan begini.
***
Seharian aku mengurung diri di kamar, ponselku pun sengaja aku matikan. Aku ingin menyendiri kalau mungkin perlu aku akan keluar kota. Untuk sementara aku berharap tak bertemu Dika. Sakit sekali setiap harus melihat wajah cowok itu ataupun mendengar suaranya. Berkali-kali ketukan pintu dan seruan Mama tak aku hiraukan.
“Risty, pacarmu telepon lagi tuh. Masak kamu nggak mau angkat juga. Ini sudah keempat kalinya lho.”
“Tolong bilang ke Dika kalau Risty benci dia,” teriakku dalam suara serak karena kebanyakan menangis. Terdengar suara helaan nafas Mama, tanda menyerah.
Esoknya, Dika berusaha menemuiku di sekolah seperti yang aku duga. Segigih apapun dia aku masih punya seribu cara untuk menghindarinya. Apa yang Dika lakukan padaku sudah melampaui batas. Dan aku tak bisa lagi menerima penjelasan apapun.
Aku berusaha menikmati kesendirianku selama beberapa hari. Tapi itu tidak mudah. Ku pikir aku akan senang dengan menjauh dari Dika. Pada kenyataannya ada kerinduan mendalam yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Raga dan jiwa begitu hampa. Seperti ada sesuatu yang hilang dalam diriku. Sesuatu yang salah dan aneh. Dan aku kian resah ketika Vivi yang baru datang langsung menarikku menuju halaman parkir SMA.
“Ris, lo kemana aja sih selama ini?”
“Maksud lo?” tanyaku tak mengerti.
“Dari semalem Hp lo nggak aktif dan gue telepon ke rumah lo juga nggak diangkat.”
“Kan gue udah bilang kalo gue sengaja biar Dika nggak bisa hubungi gue,” ujarku mengingatkan apa yang pernah ku katakan pada sahabatku itu tempo hari.
“Dan itulah masalahnya,” Vivi menegaskan dengan tak sabar, “Udah! Lo masuk ke mobil gih. Kita mesti secepetnya pergi dari sini,” desaknya setengah mendorongku.
Aku mengernyit, benar-benar bingung, “Ada apa sih? Jangan-jangan lo mau nyulik gue ya.”
“Terserah deh lo mau ngomong apa,” Vivi menutup pintu dan menyuruh sopirnya segera berangkat entah kemana aku tak tahu.
“Tapi, Vi, bentar lagi kan kita masuk. Inget lho jam pertama Fisika. Pak Harno itu killer abis dan gue nggak mau kena hukuman karena telat ataupun bolos pas pelajaran dia.”
Vivi menoleh tajam dan matanya menyipit, “Dengar, Ris, lo bisa pilih. Lo mau tetep di sekolah atau ikut gue ke rumah sakit?”
“Rumah sakit?” seruku terkejut.
Vivi mengangguk tanpa memandangku lagi, “Dika masuk rumah sakit.”
“A-apa?” aku tersentak berharap salah dengar. Seolah ada batu besar yang tiba-tiba jatuh di atas kepalaku, “Lo bercanda kan?”
“Apa gue kelihatan sedang bercanda?” sinis Vivi tajam. Ada kilat marah dalam sorot matanya, “Dia kecelakaan sepeda motor semalam. Dia pingin minta maaf langsung ke lo dan dia sengaja datang ke rumah lo. Tapi gue nggak nyangka kejadiannya bakal kayak gini.”
Aku terhenyak di tempatku. Lemas! Mendadak ada suatu kekuatan besar yang meremas hatiku. Penyesalan dan kekhawatiran luar biasa menikamku demikian hebat. Kenyataan bahwa Dika kecelakaan dalam usaha meminta maaf padaku sungguh membuatku ngilu. Sesak!
“Ris, lo nggak papa? Lo pucat banget.”
Aku menggeleng lemah, “Gimana keadaan Dika?” tanyaku masih begitu terguncang.
“Tangan kirinya patah dan gegar otak ringan,” jawab Vivi hati-hati, “Tapi lo tenang aja, dokter bilang nggak ada yang perlu dikhawatirkan,” aku tahu sahabatku itu tengah berusaha agar tidak membuatku cemas.
***
Aku trenyuh melihat Dika yang terbaring lemah di atas tempat tidur yang serba putih dengan botol infus menggantung di atasnya. Kepala dan salah satu lengannya dibebat perban sementara wajah cakepnya penuh goresan luka lecet.
“Hai!” sapanya memaksakan sebuah senyum kemudian meringis kesakitan.
Aku menghampirinya dan tanpa sadar aku sudah memeluknya, menumpahkan segala tangisku, “Kalo lo mau minta maaf ke gue
“Usaha gue nggak sia-sia
“Lo kelihatan ancur banget,” aku membalas di tengah isakku.
“Gue sayang lo, Ris.”
Deg!
Aku terpekur dan dentuman di rongga dada kian bergema.
“Nggak ada cewek lain yang bisa gantiin lo di hati gue,” lanjut Dika bersugguh-sungguh.
Ku seka air mata haru yang mulai jatuh, “Gue percaya,” ujarku masih dengan perasaan bersalah.
“Oya, ini Gwen.”
Aku berpaling ke sosok kucing
“Gwen?” gumamku meneguk ludah, “Dia—Gwen?”
“Ya.”
“Jadi selama ini gue jealous sama—KUCING?” seruku masih tak percaya.
Dika mengiyakan seraya menahan tawa sementara di belakangku Vivi ngakak. Seumur hidup aku tak pernah semalu ini. Pasti sekarang mukaku semerah tomat. Aduh nggak tahu mesti ngomong apa. Sebel tapi lucu juga. Habisnya nama tuh kucing lebih keren dari aku, jadi aku pikir Gwen siapa. Yang jelas, dari kejadian ini aku yakin cinta Dika hanya untukku …
Karya : Sri Sugiarti




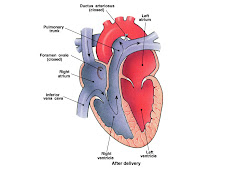











.jpg)
















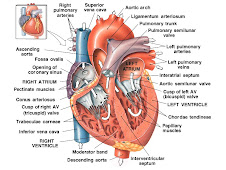






.jpg)












