a. Definisi
Anemia secara umum adalah turunnya kadar hemoglobin kurang dari 12 gram persen pada wanita tidak hamil dan kurang dari 10 gram persen pada wanita hamil (Manuaba I.B.G, 2002: 51). Anemia adalah suatu keadaan dimana eritrosit yang beredar atau konsentrasi hemoglobin menurun. Sebagai akibatnya anemia lazim terjadi dan biasanya terjadi oleh defisiensi zat besi sekunder terhadap kehilangan darah sebelumnya atau masukan besi yang tidak adekuat (Tabel B, 2001: 84).
Ibu hamil dikatakan anemia apabila kadar hemoglobin 11 gram persen pada trimester 1 dan 3 atau kurang dari 10,5 gram persen pada trimester 2 (JNPKKR-POGI, 2002: 281).
Anemia yang terkait dengan kehamilan adalah anemia defisiensi zat besi yaitu anemia yang disebabkan oleh karena kekurangn zat besi dalam darah, merupakan jenis anemia yang pengobatannya relatif mudah bahkan murah (Manuaba I.B.G, 1998: 29).
Anemia dalam kehamilan menyebabkan ibu hamil mengalami hipoksia yang dapat menyebabkan syok dan kematian ibu pada persalinan sulit, walaupun tidak terjadi perdarahan (Prawirohardjo S, 2002: 450). Karena itulah anemia memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dalam pelayanan kesehatan (Manuaba I.B.G, 1998: 40).
b. Etiologi
Anemia disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :
1) Komponen (bahan) yang berasal dari makanan, terdiri dari :
a) Protein, glukosa dan lemak
b) Vitamin B 12, B6, asam folat dan Vitamin C
c) Elemen dasar : Fe, ions Cu, Zink
2) Sumber pembentukan tulang
Tulang sumsum
3) Kemampuan reabsorpsi usus halus terhadap bahan yang diperlukan
4) Umur sel darah merah (eritrosit) terbatas sekitar 120 hari. Sel-sel darah merah yang sudah tua dibenarkan kembali menjadi bahan baku untuk membentuk sel baru.
5) Terjadinya perdarahan kronik (menahun)
a) Gangguan menstruasi
b) Penyakit yang menyebabkan perdarahan pada wanita seperti mioma uteri, polip serviks dan penyakit darah
c) Parasit dalam usus
(Manuaba I.B.G, 1998: 30)
c. Patofisiologi
Pada saat kehamilan keperluan zat-zat makanan bertambah dan terjadi pula perubahan-perubahan dalam darah dan sumsum tulang. Darah bertambah banyak dalam kehamilan (huperemia/ hipervolumia) akan tetapi pertambahan sel-sel darah kurang dibandingkan dengan bertambahnya plasma, sehingga terjadi pengenceran darah. Perbandingan pertambahan tersebut adalah plasma (30%), sel darah (18%) dan hemoglobin (19%) (Prawirohardjo S, 2002: 448).
Disamping itu kehamilan memerlukan tambahan zat besi untuk meningkatkan jumlah sel darah merah dan membentuk sel darah merah janin dan plasenta. Makin sering seorang wanita mengalami kehamilan dan melahirkan akan makin banyak kehilangan zat besi dan menjadi makin anemis (Manuaba I.B.G, 1998: 29).
d. Klasifikasi
Pembagian anemia secara garis besar dibagi menjadi :
1) Anemia dengan defisiensi besi :
Anemia defisiensi besi yaitu anemia yang disebabkan karena kekurangan zat besi.
Anemia defisiensi zat besi mencerminkan kemampuan sosial ekonomi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam jumlah dan kualitas makanan yang memadai (Manuaba I.B.G, 2001: 51).
2) Anemia megaloblastik
Yaitu anemia yang disebabkan karena difisiensi asam folik (pterolgylutamic acid), jarang sekali karena defisiensi vitamin B12 (cyanocobalamin).
3) Anemia hipoplastik
Yaitu anemia yang disebabkan karena sumsum tulang kurang mampu membuat sel-sel darah baru.
4) Anemia hemolitik
Yaitu anemia disebabkan karena penghancuran sel darah merah berlangsung lebih cepat dari pembuatannya (Prawirohardjo S, 2002: 453).
e. Penilaian Klinik menurut Manuaba I.B.G, 2001 dan Dinkes RI, 2001.
1) Tanda dan gejala
Pada anemia tanda dan gejala yang muncul dapat dibedakan menjadi :
a) Anemia ringan meliputi :
(1) Pusing, cepat lelah
(2) Prestasi kerja menurun
b) Anemia sedang meliputi :
(1) Tampak anemia
(2) Pusing-pusing
(3) Nyeri dada
(4) Sukar bernafas (Manuaba I.B.G, 2001: 51)
c) Anemia berat meliputi :
(1) Wajah pucat
(2) Cepat lelah
(3) Kuku pucat kebiruan
(4) Kelopak mata sangat pucat (Dinkes RI, 2001: 30)
2) Diagnosis
Untuk menegakkan diagnosis anemia kehamilan dapat dilakukan dengna anamnesa. Pemeriksaan dan pengawasan hemoglobin dapat dilakukan dengan menggunakan alat sahli. Hasil pemeriksaan hemoglobin dengan sahli dapat digolongkan sebagai berikut :
a) Kadar hemoglobin (11 gram%) tiadak anemia
b) Kadar hemoglobin (9-10 gram%) anemia ringan
c) Kadar hemoglobin (7-8 gram%) anemia sedang
d) Kadar hemoglobin (< 7 gram%) anemia berat
Pemeriksaan darah dilakukan minimal dilakukan selama 2 kali selama hamil, yaitu 1 kali trimester 1 dan 1 kali pada trimester 3 (Manuaba I.B.G, 1998: 30).
f. Pengaruh Anemia pada Kehamilan dan Janin
1) Pengaruh terhadap kehamilan
a) Hamil muda (trimester I)
(1) Abortus
(2) Missed abortus
(3) Kelainan konginetal
b) Trimester 2
(1) Persalinan prematur
(2) Perdarahan antepartum
(3) Gangguan pertumbuhan janin dalam rahim
(4) Asfiksia intrauterine sampai kematian
(5) Berat Badan Lahir Rendah
(6) Gestosis dan mudah terkena infeksi
(7) IQ rendah
(8) Dekompensasio kodis-kematan ibu
c) Saat persalinan
(1) Gangguan his primer dan sekunder
(2) Janin lahir dengan anemia
(3) Persalinan dengan tindakan tinggi
Meliputi : (a) Ibu cepat lelah
(b) Gangguan perjalanan persalinan perlu
tindakan operatif.
d) Masa nifas
(1) Atonia uteri menyebabkan perdarahan
(2) Retensio plasenta
(3) Perlukaan sukar sembuh
(4) Mudah terjadi febris puerperalis
(5) Gangguan involusi uteri
(6) Kematian ibu tinggi
Meliputi : - Perdarahan
- Infeksi puerperalis
- Gestosis
(Manuaba I.B.G, 2001: 52-52).
2) Pengaruh terhadap janin
Pengaruh anemia terhadap janin, meliputi :
a) Abortus
b) Terjadi kematian intrauterine
c) Persalinan prematuritas tinggi
d) Berat Badan Lahir Rendah
e) Kelahiran dengan anemia
f) Dapat terjadi cacat bawaan
g) Bayi mudah mendapat infeksi sampai kematian perinatal
h) Intelegensia rendah (Manuaba I.B.G, 1998: 32).
g. Penatalaksanaan
1) Anemia Zat Besi
Terapi oral lebih disukai, biasanya tablet ferosulfat 225 mg 2x1 sehari. Setiap tablet memberikan unsur besi 65 mg. Respon retikulosit harus diperhatikan dalam 1 minggu serta hematokrit dan hemoglobin harus mulai meningkat segera setelah itu. Pentingnya meneruskan terapi harus ditekankan, karena cadangan besi sumsum tulang harus diisi lagi.
Terapi besi parental dapat diindikasikan bila ada defisiensi besi berat dan pasien tidak dapat mentoleransi besi orang atau bila diperlukan restorasi hemoglobin yang cepat kira-kira 250 mg dekstran besi (imferon) diperlukan untuk setiap 1,0 g/100 ml kekurangan dalam konsentrasi hemoglobin (Ben_Zion Taber, M.D: 89).
2) Anemia Megaloblastik
Asam folat 1 mg per oral sekali sehari, biasanya menghasilkan retikulositosis yang mencolok (striking) dalam empat atau lima hari. Tambahan besi harus diberikan sebab sintesis hemoglobin yang cepat membutuhkan besi tambahan (Ben_Zion Taber, M.D: 89).
3) Anemia Hipolastik
Selama kehamilan tidak diperlukan untuk menaikkan kadar hemoglobin pasien di atas kadar yang biasanya selama tidak hamil (sering dalam rentang 79/100 ml). Selama persalinan dan kelahiran, tranfusi eritrosit padat (packed red cell) mungkin diperlukan. Tambahkan asam folat 1 mg sehari dianjurkan, tetapi tambahan besi biasanya tidak dibutuhkan, terapi oksigen harus diberikan selama ada peningkatan kebutuhan oksigen.
4) Anemia Hemolitik
Bila mungkin, agen hemolitik (darah tak cocok, toksin kimia atau bakteri) harus disingkirkan (Ben_Zion Taber, M.D, 2001: 89).
Jumat, 06 Februari 2009
Kehamilan Normal
a. Definisi
- Kehamilan : Suatu masa yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin (Maternal dan Neonatal, 2002: 22).
- Kehamilan : Pertumbuhan dan perkembangan janin intra uterin mulai sejak konsepsi dan berakhir sampai persalinan (Manuaba, 1998: 32).
- Kehamilan : Suatu masa yang dimulai dari ovulasi sampai persalinan yang lamanya kira-kira 280 hari (40 minggu) dan tidak lebih dari 300 hari (43 minggu).
b. Klasifikasi
Kehamilan dibagi menjadi 3 bagian :
1) Kehamilan trimestar I (0 – 12 minggu)
2) Kehamilan trimester II (13 – 27 minggu)
3) Kehamilan trimester III (28 – 40 minggu)
c. Proses Kehamilan
Kehamilan terjadi karena adanya persetubuhan antara wanita dan pria, dimana wanita tersebut dalam masa subur (ovulasi) dan pria mengeluarkan spermatozoa yang dapat membuahi sel telur kemudian berimplantasi dan tertanam di dinding endometrium, suatu proses kehamilan akan terjadi bila terdapat aspek penting, yaitu :
- Ovum/ovulasi
- Spermatozoa
- Konsepsi
- Nidasi
- Placentasi
1) Ovulasi
Ovulasi adalah pelepasan ovum yang dipengaruhi oleh sistem hormonal yang kompleks. Selama masa subur yang berlangsung 20-35 tahun hanya 420 buah ovum yang dapat mengikuti proses pematangan dan terjadi ovulasi. Ovum adalah sel besar yang terdiri dari nukleus dan vitellus dilingkari oleh zona pellusida dan dilapisi oleh corona radiata.
Urutan pertumbuhan (oogenesis) :
a) Oogenia
b) Oosit pertama
c) Primary ovarium follicle
d) Uquor follicle
e) Pematangan pertama ovum
f) Pematangan kedua ovum pada waktu sperma membuahi ovum
2) Spermatozoa
Spermatozoa berbentuk seperti kecebong yang terdiri dari 3 bagian, yaitu :
a) Kepala : Berbentuk lonjong agak gepeng yang mengandung inti
b) Leher : Penghubung antara kepala dan leher.
c) Ekor : Panjang sekitar 10 x kepala
Urutan pertumbuhan sperma (spermatogenesis) :
a) Spermatogonium membelah menjadi 2
b) Spermatosid pertama membelah 2
c) Spermatosid kedua membelah 2
d) Spermatid kemudian tumbuh
e) Spermatozoon (sperma)
3) Konsepsi
Pembuahan adalah suatu peristiwa pertemuan antara sperma dengan ovum yang terjadi di ampula tuba, pada hari ke 11-14 dalam siklus menstruasi. Wanita mengalami ovulasi yaitu peristiwa matangnya sel telur sehingga siap dibuahi bila saat itu dilakukan koitus, sperma yang mengandung <> 32 minggu ® keluhan sesak napas karena uterus mendesak isi abdomen ® diafragma.
- Kebutuhan O2 20% ® nafas dalam.
10) Kulit
Terdapat pigmentasi pada kulit karena pengaruh MSH yang meningkat.
i. Penatalaksanaan
1) Kebijakan program
- Kunjungan antenatal sebaiknya dilakukan paling sedikit 4x dalam kehamilan.
Trimester I (0-12 minggu) : 1 x
Trimester II (13-27 minggu) : 1x
Trimester III (28-40 minggu) : 2 x
- Pelayanan/ asuhan standar minimal, termask “TT”.
a) (Timbang) berat badan
b) Ukur (tekanan) darah
c) Ukur (tinggi) fundus uteri
d) Pemberian imunisasi (tetanus toksoid) TT lengkap
e) Pemberian tablet zat besi, minimum 90 tablet selama kehamilan.
f) Tes terhadap PMS
2) Kebijakan teknis
Setiap kehamilan dapat berkembang menjadi masalah atau komplikasi setiap saat, itu sebabnya mengapa ibu hamil memerlukan pemantauan selama kehamilannya.
Penatalaksanaan ibu hamil secara keseluruhan meliputi komponen-komponen sebagai berikut :
a) Mengupayakan kehamilan yang sehat
b) Melakukan deteksi dini komplikasi, melakukan penatalaksanaan awal serta rujukan bila diperlukan.
c) Persiapan persalinan yang bersih dan aman.
d) Perencanaan antisipasif dan persiapan diri untuk melakukan rujukan jika terjadi komplikasi.
3) Kunjungan Awal
Langkah/ tugas bidan dalam asuhan kunjungan awal :
a) Menyambut ibu : perkenalan, tanya nama dan usia
b) Anamnesa : riwayat kehamilan, kesehatan, sosek.
c) Pemeriksaan fisik : Inspeksi, palpasi, auskultsai dan perkusi
d) Tes laboratorium : Hb, protein urin dan glukosa urin
e) KIE : Informasi hasil pemeriksaan, ketidaknyamanan yang mungkin terjadi, tanda bahaya pada kehamilan.
f) Promosi kesehatan : Imunisasi TT, tablet Fe, vitamin A
g) Persiapan persalinan (penolong, tempat, peralatan yang dibutuhkan, biaya, transportasi, donor darah)
h) Kesimpulan dari kunjungan, jadwal kunjungan ulang dan dokumentasi
4) Kunjungan Ulang
- Kunjungan I (0-24 minggu)
Penapisan dan pengobatan anemia
Perencanaan persalinan
Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya
- Kunjungan II (24-28 minggu) dan kunjungan III (28-36 minggu)
Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya
Penapisan preeklamsi, gemelly, infeksi alat reproduksi dan saluran perkemihan mengulang perencanaan persalinan.
- Kunjungan IV (36 minggu sampai lahir)
Sama seperti kunjungan II dan III
Mengenai adanya kelainan letak dan presentasi
Memantapkan rencana persalinan
Mengenal tanda-tanda persalinan
5) Pengobatan
Pemberian tablet Fe dan vitamin
Dimulai dengan memberikan satu tablet zat besi sehari sesegera mungkin setelah rasa mual hilang, tiap tablet mengandung FeSO4 320 mg (zat besi 60 mg) dan asam folat 500 mg, minimal masing-masing 90 tablet. Tablet besi sebaiknya tidak diminum bersama-sama teh atau air jeruk.
6) Imunisasi TT
Antigen internal
cm perlindungan
% perlindungan
(selang waktu minimal)
TT1 Pada kunjungan antenatal pertama, perlindungan -
TT2 4 mgg setelah TT1 perlindungan 3 tahun, 80%
TT3 6 bulan setelah TT2 perlindungan 5 tahun, 95%
TT4 1 tahun setelah TT3 perlindungan 10 tahun, 99%
TT5 1 tahun setelah TT4 perlindungan 25 tahun atau seumur hidup, 99%
7) Kebutuhan gizi bumil
- Terjadi peningkatan sebesar 15%
Yang dibutuhkan untuk pertumbuhan uterus, mammae, volume darah, placenta, air ketuban, dan pertumbuhan janin (40% untuk pertumbuhan janin, 60% untuk pertumbuhan ibunya).
- Protein 80 gr/hari, sekitar 70% untuk pertumbuhan janin.
- Karbohidrat dan lemak
Diperlukan tambahan sebesar 300 kal/ hari atau 15% lebih banyak dari jumlan normal. Sumber : beras, tepung, ubi, jagung, sagu.
- Air, vitamin, mineral
Jenis mineral :
a) Zat kapur kebutuhan bertambah 400 mg.
Sumber : Susu, keju, sayuran hijau, kacang-kacangan
b) Fosfor kebutuhan bertambah 400 mg.
c) Kalium kebutuhan bertambah 400 mg.
d) Fe kebutuhan bertambah 30 mg.
Sumber : Ikan, hati, telur, sayuran hijau
e) Yodium kebutuhan bertambah 175 mg
Sumber : Ikan laut, minyak ikan, garam beryodium
Jenis vitamin
a) Vitamin A : 800 mikrogram
Sumber : Telur, hati, mentega, sayuran dan buah kering
b) Vitamin B6 (piridoxyne) : 2,2 mg
Sumber : Gandum, jagung, hati dan daging
c) Vitamin 12 : 2,2 mikrogram
Sumber : Telur, daging, hati, keju, ikan laut
d) Vitamin C : 70 mg
Sumber : Hati, daging, ikan, sayuran hijau
e) Vitamin D : 10 mg
f) Asam folat : 400 mg
Sumber : Hati, daging, ikan
g) Vitamin K : 65 mikrogram
Sumber : Buah dan sayuran
8) Kebutuhan ibu hamil
a) Kebutuhan nutrisi
b) Kebutuhan eliminasi
c) Kebutuhan personal hygiene
Hygiene tubuh, kulit, rambut, mammae
d) Kebutuhan pakaian
e) Kebutuhan seksual
- Kehamilan : Suatu masa yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin (Maternal dan Neonatal, 2002: 22).
- Kehamilan : Pertumbuhan dan perkembangan janin intra uterin mulai sejak konsepsi dan berakhir sampai persalinan (Manuaba, 1998: 32).
- Kehamilan : Suatu masa yang dimulai dari ovulasi sampai persalinan yang lamanya kira-kira 280 hari (40 minggu) dan tidak lebih dari 300 hari (43 minggu).
b. Klasifikasi
Kehamilan dibagi menjadi 3 bagian :
1) Kehamilan trimestar I (0 – 12 minggu)
2) Kehamilan trimester II (13 – 27 minggu)
3) Kehamilan trimester III (28 – 40 minggu)
c. Proses Kehamilan
Kehamilan terjadi karena adanya persetubuhan antara wanita dan pria, dimana wanita tersebut dalam masa subur (ovulasi) dan pria mengeluarkan spermatozoa yang dapat membuahi sel telur kemudian berimplantasi dan tertanam di dinding endometrium, suatu proses kehamilan akan terjadi bila terdapat aspek penting, yaitu :
- Ovum/ovulasi
- Spermatozoa
- Konsepsi
- Nidasi
- Placentasi
1) Ovulasi
Ovulasi adalah pelepasan ovum yang dipengaruhi oleh sistem hormonal yang kompleks. Selama masa subur yang berlangsung 20-35 tahun hanya 420 buah ovum yang dapat mengikuti proses pematangan dan terjadi ovulasi. Ovum adalah sel besar yang terdiri dari nukleus dan vitellus dilingkari oleh zona pellusida dan dilapisi oleh corona radiata.
Urutan pertumbuhan (oogenesis) :
a) Oogenia
b) Oosit pertama
c) Primary ovarium follicle
d) Uquor follicle
e) Pematangan pertama ovum
f) Pematangan kedua ovum pada waktu sperma membuahi ovum
2) Spermatozoa
Spermatozoa berbentuk seperti kecebong yang terdiri dari 3 bagian, yaitu :
a) Kepala : Berbentuk lonjong agak gepeng yang mengandung inti
b) Leher : Penghubung antara kepala dan leher.
c) Ekor : Panjang sekitar 10 x kepala
Urutan pertumbuhan sperma (spermatogenesis) :
a) Spermatogonium membelah menjadi 2
b) Spermatosid pertama membelah 2
c) Spermatosid kedua membelah 2
d) Spermatid kemudian tumbuh
e) Spermatozoon (sperma)
3) Konsepsi
Pembuahan adalah suatu peristiwa pertemuan antara sperma dengan ovum yang terjadi di ampula tuba, pada hari ke 11-14 dalam siklus menstruasi. Wanita mengalami ovulasi yaitu peristiwa matangnya sel telur sehingga siap dibuahi bila saat itu dilakukan koitus, sperma yang mengandung <> 32 minggu ® keluhan sesak napas karena uterus mendesak isi abdomen ® diafragma.
- Kebutuhan O2 20% ® nafas dalam.
10) Kulit
Terdapat pigmentasi pada kulit karena pengaruh MSH yang meningkat.
i. Penatalaksanaan
1) Kebijakan program
- Kunjungan antenatal sebaiknya dilakukan paling sedikit 4x dalam kehamilan.
Trimester I (0-12 minggu) : 1 x
Trimester II (13-27 minggu) : 1x
Trimester III (28-40 minggu) : 2 x
- Pelayanan/ asuhan standar minimal, termask “TT”.
a) (Timbang) berat badan
b) Ukur (tekanan) darah
c) Ukur (tinggi) fundus uteri
d) Pemberian imunisasi (tetanus toksoid) TT lengkap
e) Pemberian tablet zat besi, minimum 90 tablet selama kehamilan.
f) Tes terhadap PMS
2) Kebijakan teknis
Setiap kehamilan dapat berkembang menjadi masalah atau komplikasi setiap saat, itu sebabnya mengapa ibu hamil memerlukan pemantauan selama kehamilannya.
Penatalaksanaan ibu hamil secara keseluruhan meliputi komponen-komponen sebagai berikut :
a) Mengupayakan kehamilan yang sehat
b) Melakukan deteksi dini komplikasi, melakukan penatalaksanaan awal serta rujukan bila diperlukan.
c) Persiapan persalinan yang bersih dan aman.
d) Perencanaan antisipasif dan persiapan diri untuk melakukan rujukan jika terjadi komplikasi.
3) Kunjungan Awal
Langkah/ tugas bidan dalam asuhan kunjungan awal :
a) Menyambut ibu : perkenalan, tanya nama dan usia
b) Anamnesa : riwayat kehamilan, kesehatan, sosek.
c) Pemeriksaan fisik : Inspeksi, palpasi, auskultsai dan perkusi
d) Tes laboratorium : Hb, protein urin dan glukosa urin
e) KIE : Informasi hasil pemeriksaan, ketidaknyamanan yang mungkin terjadi, tanda bahaya pada kehamilan.
f) Promosi kesehatan : Imunisasi TT, tablet Fe, vitamin A
g) Persiapan persalinan (penolong, tempat, peralatan yang dibutuhkan, biaya, transportasi, donor darah)
h) Kesimpulan dari kunjungan, jadwal kunjungan ulang dan dokumentasi
4) Kunjungan Ulang
- Kunjungan I (0-24 minggu)
Penapisan dan pengobatan anemia
Perencanaan persalinan
Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya
- Kunjungan II (24-28 minggu) dan kunjungan III (28-36 minggu)
Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya
Penapisan preeklamsi, gemelly, infeksi alat reproduksi dan saluran perkemihan mengulang perencanaan persalinan.
- Kunjungan IV (36 minggu sampai lahir)
Sama seperti kunjungan II dan III
Mengenai adanya kelainan letak dan presentasi
Memantapkan rencana persalinan
Mengenal tanda-tanda persalinan
5) Pengobatan
Pemberian tablet Fe dan vitamin
Dimulai dengan memberikan satu tablet zat besi sehari sesegera mungkin setelah rasa mual hilang, tiap tablet mengandung FeSO4 320 mg (zat besi 60 mg) dan asam folat 500 mg, minimal masing-masing 90 tablet. Tablet besi sebaiknya tidak diminum bersama-sama teh atau air jeruk.
6) Imunisasi TT
Antigen internal
cm perlindungan
% perlindungan
(selang waktu minimal)
TT1 Pada kunjungan antenatal pertama, perlindungan -
TT2 4 mgg setelah TT1 perlindungan 3 tahun, 80%
TT3 6 bulan setelah TT2 perlindungan 5 tahun, 95%
TT4 1 tahun setelah TT3 perlindungan 10 tahun, 99%
TT5 1 tahun setelah TT4 perlindungan 25 tahun atau seumur hidup, 99%
7) Kebutuhan gizi bumil
- Terjadi peningkatan sebesar 15%
Yang dibutuhkan untuk pertumbuhan uterus, mammae, volume darah, placenta, air ketuban, dan pertumbuhan janin (40% untuk pertumbuhan janin, 60% untuk pertumbuhan ibunya).
- Protein 80 gr/hari, sekitar 70% untuk pertumbuhan janin.
- Karbohidrat dan lemak
Diperlukan tambahan sebesar 300 kal/ hari atau 15% lebih banyak dari jumlan normal. Sumber : beras, tepung, ubi, jagung, sagu.
- Air, vitamin, mineral
Jenis mineral :
a) Zat kapur kebutuhan bertambah 400 mg.
Sumber : Susu, keju, sayuran hijau, kacang-kacangan
b) Fosfor kebutuhan bertambah 400 mg.
c) Kalium kebutuhan bertambah 400 mg.
d) Fe kebutuhan bertambah 30 mg.
Sumber : Ikan, hati, telur, sayuran hijau
e) Yodium kebutuhan bertambah 175 mg
Sumber : Ikan laut, minyak ikan, garam beryodium
Jenis vitamin
a) Vitamin A : 800 mikrogram
Sumber : Telur, hati, mentega, sayuran dan buah kering
b) Vitamin B6 (piridoxyne) : 2,2 mg
Sumber : Gandum, jagung, hati dan daging
c) Vitamin 12 : 2,2 mikrogram
Sumber : Telur, daging, hati, keju, ikan laut
d) Vitamin C : 70 mg
Sumber : Hati, daging, ikan, sayuran hijau
e) Vitamin D : 10 mg
f) Asam folat : 400 mg
Sumber : Hati, daging, ikan
g) Vitamin K : 65 mikrogram
Sumber : Buah dan sayuran
8) Kebutuhan ibu hamil
a) Kebutuhan nutrisi
b) Kebutuhan eliminasi
c) Kebutuhan personal hygiene
Hygiene tubuh, kulit, rambut, mammae
d) Kebutuhan pakaian
e) Kebutuhan seksual
Konsep Keluarga
a. Definisi Keluarga
Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang dipersatukan oleh hubungan darah, perkawinan, adopsi atau pengakuan sebagai anggota keluarga yang tinggal bersama, satu kesatuan/ unit yang membina kerjasama yang bersumber dari kebudayaan umum, dimana setiap anggotanya belajar dan melakukan perannya seperti yang diharapkan. Keluarga sebagai suatu sistem sosial melakukan beberapa fungsi yang paling dasar seperti memberikan keturunan, sosialisasi, psikologi, seleksi, proteksi dan sebagainya (Effendy N, 1997: 5).
b. Struktur Keluarga
Struktur keluarga menurut Effendy (1997: 33) terdiri dari bermacam-macam, diantaranya adalah :
1) Patrilineal adalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah dalam beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis ayah.
2) Matrilineal adalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah dalam beberapa generasi dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis ibu.
3) Matrilokal adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga darah istri.
4) Patrilokal adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedarah suami.
5) Keluarga kawinan adalah hubungan suami istri sebagai dasar bagi pembinaan keluarga dan beberapa sanak saudara yang menjadi bagian keluarga karena adanya hubungan dengan suami atau istri.
c. Tipe/ Bentuk Keluarga
Tipe keluarga menurut Effendy N (1997: 34) antara lain :
1) Keluarga Inti (Nuclear Family) adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.
2) Keluarga Besar (Extended Family) adalah keluarga inti ditambah dengan sanak saudara, misalnya nenek, kakek, keponakan, saudara sepupu, paman, bibi dan sebagainya.
3) Keluarga Berantai (Serial Family) adalah keluarga yang terdiri dari wanita dan pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan satu keluarga inti.
4) Keluarga duda/ janda (Single Family) adalah keluarga yang terjadi karena perceraian atau kematian.
5) Keluarga Berkomposisi (Composite) adalah keluarga yang perkawinannya berpoligami dan hidup secara bersama.
6) Keluarga Kabitas (Cahabitation) adalah dua orang menjadi satu tanpa pernikahan tetapi membentuk suatu keluarga.
d. Fungsi Keluarga Dalam Masyarakat
Menurut Effendy N (1997: 35), ada beberapa fungsi yang dapat dijalankan keluarga sebagai berikut :
1) Fungsi pendidikan. Dalam hal ini tugas keluarga adalah mendidik dan menyekolahkan anak untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depan anak bila kelak dewasa nanti.
2) Fungsi sosial anak. Tugas keluarga dalam menjalankan fungsi ini adalah bagaimana keluarga menyiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
3) Fungsi perlindungan. Tugas keluarga dalam hal ini adalah melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman.
4) Fungsi perasaan. Tugas keluarga dalam hal ini adalah menjaga secara instuitif, merasakan perasaan dan suasana anak dan anggota yang lain dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama anggota keluarga sehingga saling pengertian satu sama lain dalam menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga.
5) Fungsi religius. Tugas keluarga dalam fungsi ini adalah memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beargama dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan keyakinan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.
6) Fungsi ekonomis. Tugas kepala keluarga dalam hal ini adalah mencari sumber-sumber kehidupan dalam memenuhi fungsi-fungsi keluarga yang lain, kepala keluarga bekerja untuk memperoleh penghasilan, mengatur penghasilan tersebut sedemikan rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga.
7) Fungsi rekreatif. Tugas keluarga dalam fungsi rekreasi ini tidak selalu harus pergi ke tempat rekreasi, tetapi yang penting bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan dalam keluarga sehingga dapat mencapai keseimbangan kepribadian masing-masing anggotanya. Reaksi dapat dilakkan di rumah dengna cara nonton televisi bersama, bercerita tentang pengalaman masing-masing dan sebagainya.
8) Fungsi biologis. Tugas keluarga yang utama dalam hal ini adalah untuk meneruskan keturunan sebagai generasi penerus.
e. Kesehatan keluarga
Kesehatan keluarga adalah sehat secara fisik, mental dan sosial dimana memungkinkan setiap manusia untuk hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomis (Bapelkes, 2004: 66).
Kesehatan keluarga adalah kesehatan yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan tingkat sosial ekonomi dari masyarakat. Yang sehat merupakan produktifitas yang tinggi, mereka terbebas dari biaya-biaya obat yang tinggi, mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk belajar dan tentu juga kebahagiaan mereka sendiri. Dengan demikian kesehatan keluarga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi (Bapelkes, 2004: 65).
Menurut Bapelkes (2004: 65) faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan keluarga :
1) Faktor lingkungan hidup : Sosial ekonomi, budaya dan keadaan alam.
2) Faktor perilaku : Perilaku keluarga secara kesatuan dan keluarga anggota masyarakat sebagai individu.
3) Faktor pelayanan kesehatan : Pelayanan kesehatan secara profesional itu sendiri, baik terhadap keluarga dan masyarakat.
4) Faktor sifat genteika dan keturunan dalam keluarga.
f. Sasaran Asuhan Kesehatan Keluarga
Dalam melaksanakan asuhan keperawatan kesehatan keluarga yang menjadi prioritas utama adalah keluarga-keluarga, yang tergolong tinggi dalam bidang kesehatan, meliputi :
1) Keluarga dengan anggota keluarga dalam masa usia subur dengan masalah sebagai berikut :
a) Tingkat sosial ekonomi keluarga rendah.
b) Keluarga kurang atau tidak mampu mengatasi masalah kesehatan sendiri.
c) Keluarga dengna keturunan yang kurang baik/ keluarga dengan penyakit keturunan.
2) Keluarga dengan ibu dengan resiko tinggi kebidanan, waktu hamil :
a) Umur ibu (16 tahun atau lebih 35 tahun)
b) Menderita kekurangan gizi/ anemia
c) Menderita hipertensi
d) Primipara atau multipara
e) Riwayat persalinan dengan komplikasi
3) Keluarga dimana anak menjadi resiko tinggi, karena :
a) Lahir prematur/ BBLR
b) Berat badan sukar naik
c) Lahir dengan cacat bawaan
d) ASI ibu kurang sehingga tidak mencukupi kebutuhan bayi
e) Ibu menderita penyakit menular yang dapat mengancam bayi atau anaknya
4) Keluarga mempunyai masalah dalam hubungan antara anggota keluarga :
a) Anak yang tidak dikehendaki dan pernah dicoba untuk digugurkan.
b) Tidak ada kesesuaian pendapat antara anggota keluarga dan sering timbul cekcok dan ketegangan.
c) Ada anggota keluarga yang sering sakit.
d) Salah satu orang tua (suami/ istri) meninggal, cerai atau lari meninggalkan keluarga.
Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang dipersatukan oleh hubungan darah, perkawinan, adopsi atau pengakuan sebagai anggota keluarga yang tinggal bersama, satu kesatuan/ unit yang membina kerjasama yang bersumber dari kebudayaan umum, dimana setiap anggotanya belajar dan melakukan perannya seperti yang diharapkan. Keluarga sebagai suatu sistem sosial melakukan beberapa fungsi yang paling dasar seperti memberikan keturunan, sosialisasi, psikologi, seleksi, proteksi dan sebagainya (Effendy N, 1997: 5).
b. Struktur Keluarga
Struktur keluarga menurut Effendy (1997: 33) terdiri dari bermacam-macam, diantaranya adalah :
1) Patrilineal adalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah dalam beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis ayah.
2) Matrilineal adalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah dalam beberapa generasi dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis ibu.
3) Matrilokal adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga darah istri.
4) Patrilokal adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedarah suami.
5) Keluarga kawinan adalah hubungan suami istri sebagai dasar bagi pembinaan keluarga dan beberapa sanak saudara yang menjadi bagian keluarga karena adanya hubungan dengan suami atau istri.
c. Tipe/ Bentuk Keluarga
Tipe keluarga menurut Effendy N (1997: 34) antara lain :
1) Keluarga Inti (Nuclear Family) adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.
2) Keluarga Besar (Extended Family) adalah keluarga inti ditambah dengan sanak saudara, misalnya nenek, kakek, keponakan, saudara sepupu, paman, bibi dan sebagainya.
3) Keluarga Berantai (Serial Family) adalah keluarga yang terdiri dari wanita dan pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan satu keluarga inti.
4) Keluarga duda/ janda (Single Family) adalah keluarga yang terjadi karena perceraian atau kematian.
5) Keluarga Berkomposisi (Composite) adalah keluarga yang perkawinannya berpoligami dan hidup secara bersama.
6) Keluarga Kabitas (Cahabitation) adalah dua orang menjadi satu tanpa pernikahan tetapi membentuk suatu keluarga.
d. Fungsi Keluarga Dalam Masyarakat
Menurut Effendy N (1997: 35), ada beberapa fungsi yang dapat dijalankan keluarga sebagai berikut :
1) Fungsi pendidikan. Dalam hal ini tugas keluarga adalah mendidik dan menyekolahkan anak untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depan anak bila kelak dewasa nanti.
2) Fungsi sosial anak. Tugas keluarga dalam menjalankan fungsi ini adalah bagaimana keluarga menyiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
3) Fungsi perlindungan. Tugas keluarga dalam hal ini adalah melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman.
4) Fungsi perasaan. Tugas keluarga dalam hal ini adalah menjaga secara instuitif, merasakan perasaan dan suasana anak dan anggota yang lain dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama anggota keluarga sehingga saling pengertian satu sama lain dalam menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga.
5) Fungsi religius. Tugas keluarga dalam fungsi ini adalah memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beargama dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan keyakinan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.
6) Fungsi ekonomis. Tugas kepala keluarga dalam hal ini adalah mencari sumber-sumber kehidupan dalam memenuhi fungsi-fungsi keluarga yang lain, kepala keluarga bekerja untuk memperoleh penghasilan, mengatur penghasilan tersebut sedemikan rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga.
7) Fungsi rekreatif. Tugas keluarga dalam fungsi rekreasi ini tidak selalu harus pergi ke tempat rekreasi, tetapi yang penting bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan dalam keluarga sehingga dapat mencapai keseimbangan kepribadian masing-masing anggotanya. Reaksi dapat dilakkan di rumah dengna cara nonton televisi bersama, bercerita tentang pengalaman masing-masing dan sebagainya.
8) Fungsi biologis. Tugas keluarga yang utama dalam hal ini adalah untuk meneruskan keturunan sebagai generasi penerus.
e. Kesehatan keluarga
Kesehatan keluarga adalah sehat secara fisik, mental dan sosial dimana memungkinkan setiap manusia untuk hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomis (Bapelkes, 2004: 66).
Kesehatan keluarga adalah kesehatan yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan tingkat sosial ekonomi dari masyarakat. Yang sehat merupakan produktifitas yang tinggi, mereka terbebas dari biaya-biaya obat yang tinggi, mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk belajar dan tentu juga kebahagiaan mereka sendiri. Dengan demikian kesehatan keluarga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi (Bapelkes, 2004: 65).
Menurut Bapelkes (2004: 65) faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan keluarga :
1) Faktor lingkungan hidup : Sosial ekonomi, budaya dan keadaan alam.
2) Faktor perilaku : Perilaku keluarga secara kesatuan dan keluarga anggota masyarakat sebagai individu.
3) Faktor pelayanan kesehatan : Pelayanan kesehatan secara profesional itu sendiri, baik terhadap keluarga dan masyarakat.
4) Faktor sifat genteika dan keturunan dalam keluarga.
f. Sasaran Asuhan Kesehatan Keluarga
Dalam melaksanakan asuhan keperawatan kesehatan keluarga yang menjadi prioritas utama adalah keluarga-keluarga, yang tergolong tinggi dalam bidang kesehatan, meliputi :
1) Keluarga dengan anggota keluarga dalam masa usia subur dengan masalah sebagai berikut :
a) Tingkat sosial ekonomi keluarga rendah.
b) Keluarga kurang atau tidak mampu mengatasi masalah kesehatan sendiri.
c) Keluarga dengna keturunan yang kurang baik/ keluarga dengan penyakit keturunan.
2) Keluarga dengan ibu dengan resiko tinggi kebidanan, waktu hamil :
a) Umur ibu (16 tahun atau lebih 35 tahun)
b) Menderita kekurangan gizi/ anemia
c) Menderita hipertensi
d) Primipara atau multipara
e) Riwayat persalinan dengan komplikasi
3) Keluarga dimana anak menjadi resiko tinggi, karena :
a) Lahir prematur/ BBLR
b) Berat badan sukar naik
c) Lahir dengan cacat bawaan
d) ASI ibu kurang sehingga tidak mencukupi kebutuhan bayi
e) Ibu menderita penyakit menular yang dapat mengancam bayi atau anaknya
4) Keluarga mempunyai masalah dalam hubungan antara anggota keluarga :
a) Anak yang tidak dikehendaki dan pernah dicoba untuk digugurkan.
b) Tidak ada kesesuaian pendapat antara anggota keluarga dan sering timbul cekcok dan ketegangan.
c) Ada anggota keluarga yang sering sakit.
d) Salah satu orang tua (suami/ istri) meninggal, cerai atau lari meninggalkan keluarga.
Kebidanan Komunitas
Kebidanan berasal dari kata “bidan” yang artinya seorang yang telah mengikuti pendidikan kebidanan yang diakui oleh pemerintah setempat, telah menyelesaikan pendidikan tersebut dan lulus serta terdaftar atau mendapat izin melakukan praktek bidan (Depkes RI, 2002: 1). Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku (Kepmenkes RI, 2002: 2).
Komunitas adalah suatu sistem sosial menunjukkan bahwa semua orang bersatu untuk saling melindungi dalam kepentingan bersama dan berfungsi sebagai suatu kesatuan dan secara terus menerus mengadakan hubungan (interaksi) dengan sistem yang lebih besar. Bagian-bagian saling berinteraksi tersebut merupakan sub komuniti seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan keluarga, misalnya pelayanan KIA di Puskesmas, kunjungan rumah, melayani kesehatan ibu dan anak di lingkungan keluarga dan bukan pelayanan kebidanan yang dilakukan di rumah sakit (Effendi N, 1998: 5).
Kelompok komunitas terkecil adalah keluarga individu yang dilayani adalah bagian dari keluarga atau komunitas. Dalam melakukan pelayanan bidan tidak boleh memandang pasiennya dari sudut biologis, akan tetapi sebagai unsur sosial yang memiliki budaya tertentu dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kondisi lingkungan sekelilingnya. Dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur yang tercakup dalam kebidanan komunitas adalah bidan komunitas, pelayanan kebindanan komunitas, sasaran pelayanan kebidanan komunitas, lingkungan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Syahlan, 1999: 23).
a. Bidan Komunitas
Bidan yang bekerja melayani keluarga dan masyarakat di wilayah tertentu disebut bidan komunitas (Syahlan, 1999: 23). Sebagai tenaga kesehatan, bidan mempunyai tugas penting dalam memberi bimbingan, asuhan dan penyuluhan kepada ibu hamil, persalinan, nifas dan menolong persalinan dengan tanggung jawab sendiri serta memberikan asuhan pada bayi baru lahir. Dalam pendidikan dan Konseling tidak hanya untuk antenatal, persiapan menjadi orang tua dan meluas ke bidang tertentu dari gynaclogu, KB dan asuhan terhadap anak. Bidan membantu keluarga dan masyarakat agar selau berada di dalam kondisi kesehatan yang optimal. Bidan di masyarakat bertindak sebagai pelaksana pelayanan kebidanan. Sebagai Pelaksana bidan harus menguasai pengetahuan teknologi kebidanan (Depkes RI, 2002: 12).
b. Pelayanan Kebidanan Komunitas
Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, yang diarahkan untuk mewujudkan kesehatan keluarga dalam mewujudkan kesehatan keluarga dalam rangka tercapainya keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Pelayanan kebidanan merupakan layanan yang diberikan oleh bidan sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dengan maksud meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka tercapainya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
Pelayanan kebidanan komunitas dilaksanakan oleh bidan secara mandiri. Korelasi (kerjasama) dengan tenaga kesehatan lain yang terkait pelayanan kebidanan komunitas ini dilaksanakan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Posyandu dan praktik bidan dan di rumah pasien (Depkes RI, 2002: 16).
c. Sasaran Pelayanan Kebidanan Komunitas
Sasaran pelayanan kebidanan komunitas adalah komunitas itu sendiri. Dimana di dalam komuniti terdapat kumpulan individu yang membentuk keluarga atau kelompok masyarakat. Sasaran utama pelayanan kebidanan komunitas adalah ibu dan anak di dalam keluarga (Syahlan, 1999: 26).
d. Lingkungan
Menurut Syahlan (1999: 26) dalam memberikan pelayanan kebidanan komunitas, bidan perlu juga memperhatikan faktor lingkungan. Faktor lingkungan tersebut mencakup lingkungan fisik, sosial, flora dan fauna.
1) Lingkungan fisik
Dalam memberikan pelayanan kebidanan komunitas, kondisi fisik lingkungan sangat berpengaruh, oleh sebab itu lingkungan yang sehat harus diperhatikan karena keadaan fisik lingkungan yang tidak sehat dapat menimbulkan penyakit pada masyarakat di suatu wilayah.
2) Lingkungan sosial
Di dalam suatu komuniti dipengaruhi oleh suatu ikatan sosial budaya, kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan dan agama. Sehingga dalam memberikan pelayanan kebidanan harus dapat menyesuaikan dengan lingkungan sosial yang ada.
3) Lingkungan flora dan fauna
Di dalam kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari lingkungan flora dan fauna, oleh sebab itu peru adanya keseimbangan antara manusia dan alam untuk mencapai kelangsungan hidup manusia yang sehat.
4) Ilmu pengetahuan dan teknologi
Di jalan yang modern ini, pengetahuan masyarakat terus berkembang dan bertambah, ini sebagai akibat dari semakin maju dan bertambahnya ilmu pengetahuan dan teknologi di negara. Dalam pelayanan kebidanan komunitas harus menggunakan ilmu dan teknologi yang sesuai dengan tuntutan masyarakat.
Komunitas adalah suatu sistem sosial menunjukkan bahwa semua orang bersatu untuk saling melindungi dalam kepentingan bersama dan berfungsi sebagai suatu kesatuan dan secara terus menerus mengadakan hubungan (interaksi) dengan sistem yang lebih besar. Bagian-bagian saling berinteraksi tersebut merupakan sub komuniti seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan keluarga, misalnya pelayanan KIA di Puskesmas, kunjungan rumah, melayani kesehatan ibu dan anak di lingkungan keluarga dan bukan pelayanan kebidanan yang dilakukan di rumah sakit (Effendi N, 1998: 5).
Kelompok komunitas terkecil adalah keluarga individu yang dilayani adalah bagian dari keluarga atau komunitas. Dalam melakukan pelayanan bidan tidak boleh memandang pasiennya dari sudut biologis, akan tetapi sebagai unsur sosial yang memiliki budaya tertentu dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kondisi lingkungan sekelilingnya. Dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur yang tercakup dalam kebidanan komunitas adalah bidan komunitas, pelayanan kebindanan komunitas, sasaran pelayanan kebidanan komunitas, lingkungan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Syahlan, 1999: 23).
a. Bidan Komunitas
Bidan yang bekerja melayani keluarga dan masyarakat di wilayah tertentu disebut bidan komunitas (Syahlan, 1999: 23). Sebagai tenaga kesehatan, bidan mempunyai tugas penting dalam memberi bimbingan, asuhan dan penyuluhan kepada ibu hamil, persalinan, nifas dan menolong persalinan dengan tanggung jawab sendiri serta memberikan asuhan pada bayi baru lahir. Dalam pendidikan dan Konseling tidak hanya untuk antenatal, persiapan menjadi orang tua dan meluas ke bidang tertentu dari gynaclogu, KB dan asuhan terhadap anak. Bidan membantu keluarga dan masyarakat agar selau berada di dalam kondisi kesehatan yang optimal. Bidan di masyarakat bertindak sebagai pelaksana pelayanan kebidanan. Sebagai Pelaksana bidan harus menguasai pengetahuan teknologi kebidanan (Depkes RI, 2002: 12).
b. Pelayanan Kebidanan Komunitas
Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, yang diarahkan untuk mewujudkan kesehatan keluarga dalam mewujudkan kesehatan keluarga dalam rangka tercapainya keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Pelayanan kebidanan merupakan layanan yang diberikan oleh bidan sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dengan maksud meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka tercapainya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
Pelayanan kebidanan komunitas dilaksanakan oleh bidan secara mandiri. Korelasi (kerjasama) dengan tenaga kesehatan lain yang terkait pelayanan kebidanan komunitas ini dilaksanakan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Posyandu dan praktik bidan dan di rumah pasien (Depkes RI, 2002: 16).
c. Sasaran Pelayanan Kebidanan Komunitas
Sasaran pelayanan kebidanan komunitas adalah komunitas itu sendiri. Dimana di dalam komuniti terdapat kumpulan individu yang membentuk keluarga atau kelompok masyarakat. Sasaran utama pelayanan kebidanan komunitas adalah ibu dan anak di dalam keluarga (Syahlan, 1999: 26).
d. Lingkungan
Menurut Syahlan (1999: 26) dalam memberikan pelayanan kebidanan komunitas, bidan perlu juga memperhatikan faktor lingkungan. Faktor lingkungan tersebut mencakup lingkungan fisik, sosial, flora dan fauna.
1) Lingkungan fisik
Dalam memberikan pelayanan kebidanan komunitas, kondisi fisik lingkungan sangat berpengaruh, oleh sebab itu lingkungan yang sehat harus diperhatikan karena keadaan fisik lingkungan yang tidak sehat dapat menimbulkan penyakit pada masyarakat di suatu wilayah.
2) Lingkungan sosial
Di dalam suatu komuniti dipengaruhi oleh suatu ikatan sosial budaya, kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan dan agama. Sehingga dalam memberikan pelayanan kebidanan harus dapat menyesuaikan dengan lingkungan sosial yang ada.
3) Lingkungan flora dan fauna
Di dalam kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari lingkungan flora dan fauna, oleh sebab itu peru adanya keseimbangan antara manusia dan alam untuk mencapai kelangsungan hidup manusia yang sehat.
4) Ilmu pengetahuan dan teknologi
Di jalan yang modern ini, pengetahuan masyarakat terus berkembang dan bertambah, ini sebagai akibat dari semakin maju dan bertambahnya ilmu pengetahuan dan teknologi di negara. Dalam pelayanan kebidanan komunitas harus menggunakan ilmu dan teknologi yang sesuai dengan tuntutan masyarakat.
Selasa, 03 Februari 2009
Hipertensi
Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan masalah yang sudah umum dewasa ini.
Klasifikasi :
Prahipertensi, sistole <139>170 mmHg, diastole >110 mmHg
Meningkatnya stressor dalam kehidupan sekarang ini menyebabkan sejumlah orang mengalami hipertensi. Adanya kecenderungan genetik, kegemukan dan asupan garam yang tinggi, semuanya merupakan faktor resiko untuk hipertensi. Jantung memompa ke arteri dengan tekanan. Besar kecil tekanan tergantung sistem arteri. Ukuran pembuluh darah ikut menentukan daya resistensi. Semakin kecil ukurannya, semakin tinggi resistensi dan semakin besar daya yang dibutuhkan untuk mendorong memompa darah ke seluruh tubuh.
Otot dinding arteri dikendalikan oleh sisten saraf simpatetik. Adanya tekanan akan merangsang dilepaskannya hormon Katekolamin yaitu noradrenalin dan adrenalin, yang menyebabkan pembuluh darah berkontraksi dan tekanan darah meningkat.
Meningkatnya tekanan darah merupakan salah satu penyebab utama terjadinya penebalan dinding arteri karena arterisklerosis. dan peningkatan kadar diastole lebih besar. semakin tinggi tekanan darah semakin cepat perkembangan penyakit, dan semakin besar kerusakan pada arteri. Hipertensi jarang menimbulkan gejala. Memeriksakan tekanan darah secara teratur merupakan suatu keharusan. Sekitar 10% kasus hipertensi disebabkan oleh gangguan ginjal dan hormon. Sisanya, 90% tidak ditemukan adanya penyebab fisik. Tipe ini disebut hipertensi esensial. Banyak dokter meyakini bahwa kepribadian dan stres merupakan faktor penting dalam hipertensi esensial. Kepribadian tipe A adalah salah satu tipe kepribadian yang memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena hipertensi dan penyakit jantung.
Klasifikasi :
Prahipertensi, sistole <139>170 mmHg, diastole >110 mmHg
Meningkatnya stressor dalam kehidupan sekarang ini menyebabkan sejumlah orang mengalami hipertensi. Adanya kecenderungan genetik, kegemukan dan asupan garam yang tinggi, semuanya merupakan faktor resiko untuk hipertensi. Jantung memompa ke arteri dengan tekanan. Besar kecil tekanan tergantung sistem arteri. Ukuran pembuluh darah ikut menentukan daya resistensi. Semakin kecil ukurannya, semakin tinggi resistensi dan semakin besar daya yang dibutuhkan untuk mendorong memompa darah ke seluruh tubuh.
Otot dinding arteri dikendalikan oleh sisten saraf simpatetik. Adanya tekanan akan merangsang dilepaskannya hormon Katekolamin yaitu noradrenalin dan adrenalin, yang menyebabkan pembuluh darah berkontraksi dan tekanan darah meningkat.
Meningkatnya tekanan darah merupakan salah satu penyebab utama terjadinya penebalan dinding arteri karena arterisklerosis. dan peningkatan kadar diastole lebih besar. semakin tinggi tekanan darah semakin cepat perkembangan penyakit, dan semakin besar kerusakan pada arteri. Hipertensi jarang menimbulkan gejala. Memeriksakan tekanan darah secara teratur merupakan suatu keharusan. Sekitar 10% kasus hipertensi disebabkan oleh gangguan ginjal dan hormon. Sisanya, 90% tidak ditemukan adanya penyebab fisik. Tipe ini disebut hipertensi esensial. Banyak dokter meyakini bahwa kepribadian dan stres merupakan faktor penting dalam hipertensi esensial. Kepribadian tipe A adalah salah satu tipe kepribadian yang memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena hipertensi dan penyakit jantung.
Merokok dan Penyakit Jantung
Tidak diragukan lagi bahwa merokok merupakan salah satu penyebab utama kematian dini dan penyakit jantung. Selama bertahun-tahun industri rokok telah menggunakan berbagai macam metode untuk menyembunyikan informasi ini dari konsumen. Parahnya lagi, mereka mendorong generasi muda untuk mulai merokok.
Semakin besar jumlah rokok yang diisap, semakin besar pula resiko terkena penyakit jantung koroner. Para perokok memiliki resiko sekitar 3-9 kali lebih besar terkena penyakit jantung koroner dibanding yang bukan perokok. Bahkan asap rokok yang dihirup bisa membuat anggota keluarga dan anak-anak terkena stroke, kanker, asma, dan kelainan pembekuan darah. Asap rokok mengandung tar penyebab kanker dan karbon monoksida (CO) yang berbahaya.
CO akan berikatan dengan haemoglobin (Hb) dan mengambil tempat oksigen dalam darah. Asap rokok juga dapat merusak dinding arteri dan mempercepat penimbunan kolesterol pada dinding arteri. Nikotin dalam rokok jika dihirup akan menyebabkan keluarnya hormon Katekolamin dan meningkatkan tekanan darah dengan cepat, memicu aritmia, dan pada beberapa kasus dapat berakibat fatal.
Sekalipun merokok hanya sekali sehari, tetap dapat meningkatkan resiko terkena penyakit jantung. Dan bagi yang telah memiliki penyakit jantung, tetap merokok merupakan tindakan bunuh diri.
Semakin besar jumlah rokok yang diisap, semakin besar pula resiko terkena penyakit jantung koroner. Para perokok memiliki resiko sekitar 3-9 kali lebih besar terkena penyakit jantung koroner dibanding yang bukan perokok. Bahkan asap rokok yang dihirup bisa membuat anggota keluarga dan anak-anak terkena stroke, kanker, asma, dan kelainan pembekuan darah. Asap rokok mengandung tar penyebab kanker dan karbon monoksida (CO) yang berbahaya.
CO akan berikatan dengan haemoglobin (Hb) dan mengambil tempat oksigen dalam darah. Asap rokok juga dapat merusak dinding arteri dan mempercepat penimbunan kolesterol pada dinding arteri. Nikotin dalam rokok jika dihirup akan menyebabkan keluarnya hormon Katekolamin dan meningkatkan tekanan darah dengan cepat, memicu aritmia, dan pada beberapa kasus dapat berakibat fatal.
Sekalipun merokok hanya sekali sehari, tetap dapat meningkatkan resiko terkena penyakit jantung. Dan bagi yang telah memiliki penyakit jantung, tetap merokok merupakan tindakan bunuh diri.
Cerpen Kids 2
NURI DAN BURUNG GEREJA
Pagi-pagi benar, burung gereja telah pergi, keluar dari sarangnya. Ia terbang membelah langit dan hinggap di puncak tiang listrik bersama sederatan burung gereja lainnya. Kala fajar menyingsing, saat yang tepat baginya. Butir-butir beras yang berserakan adalah sasarannya. Ia pun terbang menukik dan mendarat di atas tanah yang becek oleh guyuran hujan. Semalaman hujan terus turun tak kunjung henti. Namun, pagi ini cuaca tampaknya cukup cerah.
Baginya mencari makan di pagi hari sudah menjadi rutinitasnya. Kadang ia berpikir sandainya ia secantik Merpati, Cendrawasih, Beo dan burung-burung lainnya, pasti akan ada manusia yang mau merawatnya. Andai ada manusia yang memeliharanya, ia tak perlu repot mencari makanan dalam pagi yang dingin seperti ini. Ia akan punya sangkar yang hangat dan nyaman. Namun hal-hal seperti itu rasanya tak mungkin terjadi pada seekor burung gereja.
Ia pun mematuk biji demi biji beras. Beberapa burung gereja lainnya tampak tengah mengikuti tindakannya. Salah satu burung gereja bercuit riang dan yang lain pun menyahut. Ia berhenti mematuk ketika didengarnya suara nyanyian panjang yang memecah keheningan. Nyanyian seekor burung yang terdengar lebih menyerupai sebuah ratapan penuh kesedihan
Ia pun terbang menembus udara beku dan kabut pekat. Cahaya mentari masih begitu redup, hangatnya tak seberapa. Tetes-tetes embun pun bergayut di tiap pucuk dedaunan yang hijau segar. Si burung gereja mencoba mencari asal suara ratapan itu. Dan Ia pun berhenti di depan sebuah rumah besar layaknya istana.
Ia menelengkan kepalanya, memandang berkeliling. Dan matanya yang bulat coklat menangkap bayangan seekor Nuri cantik berwarna kuning dengan semburat hijau di sayapnya. Burung Nuri itu terus mengeluarkan nyanyian sendunya seakan tidak menyadari kehadiran si burung gereja.
“Kelihatannya kau sedang bersedih,” kata burung gereja tiba-tiba, membuat Nuri itu menghentikan nyanyiannya.
“Kau? Bagaimana bisa kau ke sini?” tanya Nuri keheranan. Ia tampak begitu cantik dalam sangkar emas yang besar, sementara itu burung gereja terus memperhatikan sangkar yang berkilauan tertimpa cahaya matahari
Andai saja aku punya tempat tinggal seindah ini dan bukannya sarang dari jerami kering. Pikir burung gereja iri.
“Hei, kau belum jawab pertanyaanku,” seru Nuri dengan suara melengking tinggi, “Kenapa kau ada di sini?”
“Aku mendengar nyanyianmu,” ucap burung gereja akhirnya, “Nyanyianmu terdengar begitu sedih, jadi aku kemari.”
Wajah nuri seketika itu kembali muram dan ia menggelelng, “Yah kau benar.”
“Memangnya apa yang membuatmu murung seperti itu?”
“Aku ingin pergi dari sini.”
Burung gereja terkejut mendengar ucapan Nuri, “Kenapa? Bukankah seharusnya kau bahagia menjadi hewan peliharaan. Tak perlu kedinginan. Makanan selalu tersedia kapanpun kau mau.”
Nuri langsung melotot marah, “Tapi di sini aku tak punya teman. Aku sangat kesepian—”
“Begitu?”
“Hei, apa kau belum mengerti juga,” kata Nuri bertambah kesal, “Hal terpenting bagi makhluk Tuhan adalah kebebasan. Itu yang tidak aku miliki, kau mesti bersyukur bisa pergi kemana pun kau suka, melihat pemandangan-pemandangann indah dan punya banyak teman. Sementara aku, terus terkurung dalam sangkar ini.”
Burung gereja hanya terdiam. Kata-kata Nuri begitu menyentuh hatinya. Ia tak pernah mengira hidup sebagai hewan peliharaan akan seperti itu.
Nuri benar, Tuhan menciptakan setiap makhluknya baik dalam wujud yang cantik ataupun buruk pasti ada maksudnya. Seperti halnya Nuri yang cantik tapi tidak bahagia karena terus terkurung dalam sangkar emasnya.
Walaupun burung gareja tidak secantik burung-burung lainnya, tapi ia memiliki kebebasann dan itu adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Dan setiap makhluk Tuhan seharusnya bersyukur atas setiap yang dimilikinya.
Karya Sri Sugiarti
atty_131186@yahoo.com
Pagi-pagi benar, burung gereja telah pergi, keluar dari sarangnya. Ia terbang membelah langit dan hinggap di puncak tiang listrik bersama sederatan burung gereja lainnya. Kala fajar menyingsing, saat yang tepat baginya. Butir-butir beras yang berserakan adalah sasarannya. Ia pun terbang menukik dan mendarat di atas tanah yang becek oleh guyuran hujan. Semalaman hujan terus turun tak kunjung henti. Namun, pagi ini cuaca tampaknya cukup cerah.
Baginya mencari makan di pagi hari sudah menjadi rutinitasnya. Kadang ia berpikir sandainya ia secantik Merpati, Cendrawasih, Beo dan burung-burung lainnya, pasti akan ada manusia yang mau merawatnya. Andai ada manusia yang memeliharanya, ia tak perlu repot mencari makanan dalam pagi yang dingin seperti ini. Ia akan punya sangkar yang hangat dan nyaman. Namun hal-hal seperti itu rasanya tak mungkin terjadi pada seekor burung gereja.
Ia pun mematuk biji demi biji beras. Beberapa burung gereja lainnya tampak tengah mengikuti tindakannya. Salah satu burung gereja bercuit riang dan yang lain pun menyahut. Ia berhenti mematuk ketika didengarnya suara nyanyian panjang yang memecah keheningan. Nyanyian seekor burung yang terdengar lebih menyerupai sebuah ratapan penuh kesedihan
Ia pun terbang menembus udara beku dan kabut pekat. Cahaya mentari masih begitu redup, hangatnya tak seberapa. Tetes-tetes embun pun bergayut di tiap pucuk dedaunan yang hijau segar. Si burung gereja mencoba mencari asal suara ratapan itu. Dan Ia pun berhenti di depan sebuah rumah besar layaknya istana.
Ia menelengkan kepalanya, memandang berkeliling. Dan matanya yang bulat coklat menangkap bayangan seekor Nuri cantik berwarna kuning dengan semburat hijau di sayapnya. Burung Nuri itu terus mengeluarkan nyanyian sendunya seakan tidak menyadari kehadiran si burung gereja.
“Kelihatannya kau sedang bersedih,” kata burung gereja tiba-tiba, membuat Nuri itu menghentikan nyanyiannya.
“Kau? Bagaimana bisa kau ke sini?” tanya Nuri keheranan. Ia tampak begitu cantik dalam sangkar emas yang besar, sementara itu burung gereja terus memperhatikan sangkar yang berkilauan tertimpa cahaya matahari
Andai saja aku punya tempat tinggal seindah ini dan bukannya sarang dari jerami kering. Pikir burung gereja iri.
“Hei, kau belum jawab pertanyaanku,” seru Nuri dengan suara melengking tinggi, “Kenapa kau ada di sini?”
“Aku mendengar nyanyianmu,” ucap burung gereja akhirnya, “Nyanyianmu terdengar begitu sedih, jadi aku kemari.”
Wajah nuri seketika itu kembali muram dan ia menggelelng, “Yah kau benar.”
“Memangnya apa yang membuatmu murung seperti itu?”
“Aku ingin pergi dari sini.”
Burung gereja terkejut mendengar ucapan Nuri, “Kenapa? Bukankah seharusnya kau bahagia menjadi hewan peliharaan. Tak perlu kedinginan. Makanan selalu tersedia kapanpun kau mau.”
Nuri langsung melotot marah, “Tapi di sini aku tak punya teman. Aku sangat kesepian—”
“Begitu?”
“Hei, apa kau belum mengerti juga,” kata Nuri bertambah kesal, “Hal terpenting bagi makhluk Tuhan adalah kebebasan. Itu yang tidak aku miliki, kau mesti bersyukur bisa pergi kemana pun kau suka, melihat pemandangan-pemandangann indah dan punya banyak teman. Sementara aku, terus terkurung dalam sangkar ini.”
Burung gereja hanya terdiam. Kata-kata Nuri begitu menyentuh hatinya. Ia tak pernah mengira hidup sebagai hewan peliharaan akan seperti itu.
Nuri benar, Tuhan menciptakan setiap makhluknya baik dalam wujud yang cantik ataupun buruk pasti ada maksudnya. Seperti halnya Nuri yang cantik tapi tidak bahagia karena terus terkurung dalam sangkar emasnya.
Walaupun burung gareja tidak secantik burung-burung lainnya, tapi ia memiliki kebebasann dan itu adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Dan setiap makhluk Tuhan seharusnya bersyukur atas setiap yang dimilikinya.
Karya Sri Sugiarti
atty_131186@yahoo.com
Langganan:
Postingan (Atom)




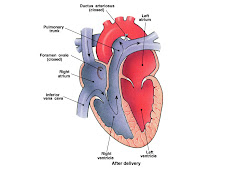











.jpg)
















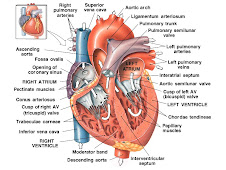






.jpg)












