Dua minggu berlalu sangat cepat dan Mona seakan telah melupakan segenap kegelisahannya baik perihal cowok itu maupun soal Golden Village. Suasana di kota itu juga cukup menyenangkan ditambah keramahan Tante Linda dan Om Billy. Hanya satu kata yang bisa menggambarkannya.Fun abiz!
“Flo, gue jalan-jalan dulu ya,” kata Mona meminta ijin. Tante Linda yang saat itu juga ada di kamar Florence mempersilakan dengan senyum lebar.
“Jangan jauh-jauh ya,” gumam wanita muda yang belum dikaruniai anak itu.
“Iya, cuma disekitar sini kok, Tante,” sahut Mona, “Mumpung masih pagi. Di luar pasti masih seger banget.”
Florence mendongak dan memasukkan legging pinknya ke dalam koper, “Sendirian nggak papa kan? Gue belum selesai beres-beres nih.”
“Nggak papa.”
“Tapi jangan sampai lupa waktu ya. Habis duhur kita berangkat cause kita juga belum beli tiket jadi mesti datang lebih awal. Kita pakai kereta yang jam 13.30. So don’t be late!” Florence mewanti-wanti dengan tampang galak.
“Gue tau,” ucap Mona nyengir kuda dan ia beralih pada Tante Linda yang membantu Florence memasukkan peralatan make up ke box kosmetik khusus, “Mona permisi dulu, Tante.”
“Hati-hati ya. Jangan sampai nyasar lho.”
“Kalo nyasar gue nggak mau cariin lo,” tambah Florence berkelakar.
“Iya,” Mona yang sudah di luar kamar dan tengah menuruni tangga, berseru lantang.
Hari masih pagi benar. Dan inilah yang paling Mona suka, menghirup nafas dalam-dalam dan membiarkan udara dingin nan sejuk memenuhi paru-parunya. Kabut pekat tampak bergayut rendah dan embun di pucuk dedaunan layaknya perawan yang baru selesai mandi. So fresh! Sementara di ufuk timur, mentari tersenyum malu menyambut Mona, membiarkan kehangatannya menyentuh kulit gadis itu.
“Jarang-jarang gue bisa liat petak-petak sawah kayak gini,” gumam Mona menyusuri jalan tanah yang lebarnya tak lebih dari semester, “Ini nih yang namanya cuci mata,” decaknya kagum melayangkan pandang ke bentangan karpet alam nan hijau. Baru beberapa ratus meter ia berjalan ketika tiba-tiba …
KRIIIIIINGG! KRIIIIIING!
Dering sepeda itu memecahkan kesunyian dan menjerit nyaring di antara kicau burung, “AWAASSS!”
Mona berbalik, terbelalak dan berusaha menghindar sebisa mungkin. Kekagetan menguasainya dan ia terhempas. Jatuh di parit! Ia mencoba berdiri di tengah lumpur liat dengan berdecak pinggang, “EH, LO APA-APAAN SIH? KALO NGGAK BISA, YA NGGAK USAH NAIK SEPEDA! BIKIN ORANG CELAKA AJA!” teriaknya berang hingga wajahnya sama merahnya dengan tomat.
“Maaf,” kata laki-laki itu mendekat setelah menyandarkan sepedanya di batang pohon jambu.
Mona sudah membuka mulutnya siap membalas lagi dan bila perlu mungkin ia akan mengeluarkan seluruh kejutekannya. Namun, apa yang dilihatnya membuat kata-katanya tersangkut ditenggorokan.
“Lo—lo kan—” bola mata Mona melebar sampai segede jengkol. Berkali-kali ia mengerjap dan menampar pipinya mencoba meyakinkan diri kalau sosok di depannya bukanlah ilusi. Seseorang yang akhir-akhir ini menghiasi mimpinya!
“Gue Dennis. Apa lo lupa?” cowok itu mengulurkan tangan seraya membantu Mona keluar dari parit.
Mona terpana dengan tubuh membeku. Ia tak peduli lagi akan kaki maupun pakaiannya yang kini kotor dan penuh bercak coklat, “Ja—jadi lo—kenal gue?” serunya ternganga.
“He-em, lo Mona kan?” ujar Dennis, bibirnya tertarik dalam senyuman yang mampu menggetarkan hati Mona, “Udah lama gue nunggu lo, Mon. Apa lo masih nyimpen Golden Village dari gue?”
Golden Village? Jadi benar, cowok itu bagian dari masa lalu Mona? Masa lalu yang telah lama ia pertanyakan? Meski masa lalu itu hanya sedikit yang dapat diingatnya.
Rasa sesak berkecamuk di dada Mona hingga tanpa sadar butir panas itu muncul di sudut matanya, “Ya,” gumamnya pelan, menekan haru yang bergolak di jiwanya, “Gue—gue nggak nyangka bisa ketemu lo di sini. Is it real?” tanyanya masih tak percaya.
“Lo nggak mimpi, Mon, ini gue, Dennis,” Dennis meraih lengan gadis itu dan degup jantung Mona kian menggila, “I am here, just for you my princess.”
Mona tersentak. Just for you? Kata-kata itu! Masih jelas dalam ingatannya atas apa yang pernah dikatakan Dennis.
‘Just for you my Princess. It’s shinning as like your smile. Gue harap Golden Village ini bisa buat lo inget terus sama gue.’
Mona mengangguk. Tawa bahagia itu berbaur dalam leleran air mata yang tak tertahankan, “Lo selalu ada di mimpi gue. Dan gue juga nggak lupa Golden Village yang lo beri meski gue amnesia.”
“I know,” Dennis mencium tangan Mona, “Makanya gue rela nunggu lo selama bertahun-tahun. Semua demi lo, demi kita.”
Mona mendongak, “Jadi bener, lo itu pacar gue?”
“Ya,” bisik Dennis tak melepaskan genggamannya seolah ia takut untuk kehilangan Mona lagi, “Mon, apa lo masih punya perasaan yang sama ke gue?”
Mulut Mona mendadak kering. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi ia tak bisa berbohong, ada kerinduan mendalam yang menjeratnya erat-erat sampai ia merintih demikian nyeri. Kerinduan akan sosok Dennis yang telah lama terpisah darinya baik oleh jarak maupun waktu, “Gue sayang lo, Den,” isaknya.
“I do love you, my princess,” ucap Dennis bersungguh-sungguh dan jari-jarinya mengusap kristal bening yang membasahi pipi Mona, “Please don’t cry.”
Mona tertunduk. Sekian lama ia mencari cowok itu, mencari cintanya. Dan sekarang Dennis hadir di tempat dan saat yang tak pernah ia duga sebelumnya. Bagaimana bisa ia tahan untuk tidak menangis?
“Udah dong, jangan sedih lagi.”
Masih dengan rona merah, Mona memaksakan sebuah senyum, “Lo mau nggak nganterin gue jalan-jalan?”
“Apapun itu, buat lo Mon,” Dennis sedikit membungkukkan badan laksana bangsawan Eropa abad 15, “Gue ajak lo ke pantai ya, tempat kita biasa nongkrong dulu. Gimana?”
“With pleasure,” sahut Mona excited, “Jauh nggak dari sini?”
“Cuma beberapa kilo kok. Kalau pakai sepeda ya sekitar satu jam.”
“Oke deh.”
***
Dennis mengayuh sepedanya sementara hari mulai siang. Berkali-kali ia mengelap peluh yang membasahi wajahnya.
“Kenapa lo baru muncul sekarang sih?” gerutu Mona yang duduk takut-takut di boncengan belakang dan ia mencengkram sisi kaos putih Dennis untuk berpegangan, “Hari ini kan gue mesti pulang.”
“Makanya tadi gue berharap bisa ketemu lo sebelum lo balik. Dan ternyata doa gue terkabul.”
Mona tertawa. Ia tak pernah selepas ini, seakan seluruh beban dalam hidupnya luntur terkikis kebahagiaan ini, “Tapi kita masih bisa berhubungan kan?”
Dan yang ditanya hanya bungkam. Mona tidak tahu apa yang tengah dipikirkan Dennis. Ia juga tak yakin akan raut Dennis yang dilihatnya waktu itu. Tidak sedih tapi juga tidak menunjukkan rasa senang. Hampa, tanpa ekspresi.
“Den, sebenernya gue heran. Kenapa ya bonyok gue nggak pernah cerita tentang lo?” gumam Mona merenung, “Kan nggak mungkin kalo mereka nggak tau lo. Apa dulu mereka nggak setuju sama hubungan kita? Mungkin mereka sengaja pingin pisahin kita. Apalagi gue sampai amnesia.”
Dennis angkat bahu, “Nggak tau juga sih,” sahutnya singkat. Dan Mona menangkap sinyal aneh pada diri cowok itu. Sepertinya Dennis tak ingin membahas lebih lanjut tentang hal itu.
“Oya, boleh nggak gue minta nomer Hp lo?” tanya Mona lagi mencoba mengalihkan pembicaraan.
“Gue nggak punya Hp.”
Mona nyengir lebar, “Hari gini nggak punya Hp?” ledeknya meniru gaya salah satu iklan di teve.
“Mon, gue kan orang miskin. Nggak kayak lo.”
“Terus gimana dong?” Mona cemberut.
“Sebutin aja nomer Hp lo. Biar gue yang kontak lo.”
“Ok,” desah Mona mengalah. Ia pun menyebutkan 11 digit angka miliknya, “Lho kok nggak lo catat?” hardiknya ketika dilihatnya mulut Dennis komat-kamit menghafal nomor itu.
“Udah gue catat di otak gue,” ujar Dennis menyeringai hingga menampakkan deretan gigi putih rapi ala senyum Close Up, “Lo nggak usah khawatir. Kalo pas gue ada duit, gue bakal telepon lo. Lagian kalo lo kangen, lo kan bisa ke sini jenguk gue.”
Mona pun setuju, “Ngomong-ngomong rumah lo dimana?”
“Sebelah sana,” Dennis mengedikkan kepalanya ke salah satu arah, “Di deket pasar.”
“Oooo,” bibir Mona membulat.
Sepeda terus melaju dan kini mereka melewati daerah tambak. Angin berhembus semakin kencang yang menandakan laut sudah ada di depan mata. Deretan pohon bakau tumbuh di sepanjang tepi jalan dan pematang yang memisahkan antar tambak. Mona bahkan bisa melihat tanah bergaram di sekitar tempat itu.
Dan seperti yang Mona duga, lautnya luar biasa indah. Begitu biru, jernih seakan tak terjamah. Pepohonan kelapa tumbuh tinggi dengan hamparan pasir putih yang menyilaukan mata. Mona duduk di bibir pantai tepat ketika gulungan ombak datang menyambut, membiarkan riak-riak kecil air membasahi betisnya yang penuh lumpur kering.
Matahari meninggi namun Mona tak peduli teriknya yang membakar kulit. Ia juga tak peduli akan panasnya pasir yang membuat telapak kakinya melepuh. Cukuplah ia bersama Dennis, baginya itu lebih dari cukup.
“Gue suka laut ini,” komentar Mona jujur.
“Apalagi kalau senja. Laut ini jadi tempat paling romantis sedunia.”
“Senja di pantai itu!” Mona bergumam pelan layaknya bicara pada diri sendiri, “Beberapa minggu yang lalu kalimat itu selalu ada dipikiran gue. Awalnya gue nggak ngerti. Ternyata pantai ini adalah bagian dari hidup gue.”
“Mon—”
Mona berpaling.
“Ada yang mau gue omongin,” ucap Dennis tertunduk dalam, “Gue mau lo janji sama gue.”
“Janji?” Mona mengernyit. Entah kenapa mendadak perasaannya jadi tak enak.
“Apapun yang terjadi, gue nggak mau lo nyalahin diri sendiri.”
“Lo ngomong apaan sih?” seru Mona bingung. Menurutnya perkataan Dennis sudah mulai ngelantur.
“Mon, lo hilang ingatan, semua itu bukan salah lo,” kata Dennis masih dengan gumaman yang amat janggal, “Tapi yang paling penting, kecelakaan itu juga bukan salah lo.”
Mona menggeleng tak mengerti, “Gue nggak inget apa-apa, Den,” desisnya penuh tanda tanya.
“Suatu saat lo pasti inget semuanya. Butuh proses memang, tapi saatnya akan tiba.”
Cukup lama Mona memperhatikan Dennis, berharap menemukan keping masa lalunya di sana, “Jadi lo tau soal kecelakaan itu?”
Dennis diam. Ia terus menatap ke laut lepas dengan pandangan menerawang jauh. Dan ombak kembali berdebur, menyentuh kaki Mona.
“Den, lo denger gue kan?” rajuk Mona dengan tatapan memohon, “Gue pingin lo cerita tentang gue, tentang kita,” tapi Dennis tidak juga berkata sesuatu, membuat gadis itu melenguh sebal.
Mona merengut. Baru sekarang ia menyadari bahwa Dennis sungguh pribadi yang sulit dipahami. Tapi rasanya ia tahu kenapa Dennis tak mau mengatakan soal kecelakaan itu. Mungkin karena musibah itulah yang memisahkan dirinya dan Mona selama bertahun-tahun. Kecelakaan itu berhasil menggantung hubungan mereka sekian lama tanpa ada kepastian baik untuk Mona maupun Dennis.
“Den, gue boleh nggak pinjem bahu lo?” pinta Mona manja. Dan dia telah menyandarkan kepalanya saat Dennis membelai lembut rambutnya, “Gue ngantuk banget.”
“Just for you my princess,” sahut cowok itu meringis dan Mona senang Dennis kembali ceria seperti sedia kala.
***
“DEN, KOK LO NGGAK BANGUNIN GUE SIH!” Mona memekik dengan suara melengking yang mampu membangunkan orang sekampung.
Dennis melongo pasang tampang bego, “Emangnya lo pesen ke gue buat bangunin lo?”
“DENNIIIIISS!” Mona menggeram gemas, “Lo kan tau sendiri jam setengah dua ini kereta gue berangkat,” gerungnya frustasi dan ia nyaris terkena serangan jantung saat Sang Surya berubah menjadi merah menyala berlatar langit jingga keemasan.
“Apa iya lo bilang begitu?” Dennis terbengong dengan bloonnya menyebabkan Mona demikian dongkol.
“Ya udah, sekarang lo anterin gue pulang,” rutuk Mona jengkel. Sepanjang perjalanan, ia terus bersungut-sungut dan menggerundel tak jelas. Sedangkan Dennis tampak kelelahan mengayuh sepedanya dalam cahaya temaram senja.
“Bisa nggak sih lo lebih cepet lagi?” Mona yang masih ngambek menukas tajam.
“Lagian percuma, Mon. Ini tuh udah sore.”
“Gara-gara lo tau.”
“Marahnya dipending dulu dong.”
“Pending? Lo pikir mulut gue Hp?”
“Ya, bukannya gitu,” keluh Dennis dengan nada letih, “Gue capek nih. Masa lo nggak kasihan sama gue.”
“Nggak,” balas Mona sinis meski hati kecilnya tak tega melihat Dennis yang kian pucat, “Lagian lo juga sih. Coba kalo lo tadi bangunin gue, kan nggak kayak gini. Gue juga yang bakal kena semprot.”
Dan apa yang ditakutkan Mona pun terjadi. Setibanya di rumah Tante Linda, ia sudah ditodong Florence yang siap melancarkan omelannya.
“MONA, LO SADAR NGGAK SEKARANG INI JAM BERAPA?”
“Gue—” Mona sudah membuka mulutnya tapi ia segera mengurungkan niat. Ia tak pernah melihat Florence meledak seperti itu. Ia tahu apa yang dilakukannya hari ini memang sudah kelewat batas. Tapi itu bukanlah suatu kesengajaan. Sebenarnya ia sangat ingin bercerita soal Dennis dan juga pantai itu. Mungkin sekarang waktunya kurang tepat.
“Besok kan kita udah harus ke sekolah. Lo gimana sih, Mon,” bentak Florence habis kesabaran.
“Flo, jangan kasar gitu ah,” Tante Linda mencoba menengahi dan ia tersenyum menenangkan ke arah Mona yang merasa amat bersalah, “Kalian pulangnya besok aja. Nanti Tante kabari ayah kamu, Flo, biar dia yang memintakan ijin untuk kalian ke pihak sekolah.”
“Tapi bukan soal itu, Tante, Flo kecewa banget sama Mona,” seru cewek itu berapi-api.
Mona semakin tak enak hati. Ia memang telah mengacaukan segalanya, “Maafin gue, Flo.”
“Nggak papa, jangan sedih gitu dong,” hibur Tante Linda. Florence yang masih tampak berang mendengus kesal. Ia berbalik pergi dan menghempaskan dirinya keras-keras di sofa ruang keluarga.
Mona berjalan lunglai naik ke kamarnya, mengheningkan cipta. Benar apa kata Flo, ia telah sangat mengecewakan. Terlalu egois sampai menyalahkan Dennis atas kelalaiannya sendiri. Ia berbaring dengan mata tertutup, mengusir penat dan terlelap dalam tidur yang gelisah
***
Mona terbangun oleh suara ketukan pintu. Fajar belum juga bergerak dari peraduannya dan subuh baru menjelang. Mona menggeliat di kasurnya yang nyaman. Udara dingin membekukan segenap tulang dan persendiannya, “Masuk!” gumamnya dengan suara mengantuk. Ia meraba-raba meja di sebelahnya dan menyalakan saklar lampu. Seketika cahaya kekuningan memenuhi ruangan itu.
“Mon, udah bangun ya?”
Mona mengerjap-kerjapkan mata untuk melihat lebih jelas. Tampak olehnya Florence yang menempatkan diri di sebelahnya, “Oh lo, Flo,” sahutnya berusaha bangkit dan duduk, “Lo—nggak marah lagi kan—sama gue?” tanyanya takut-takut, “Sori banget ya, Flo.”
Di luar dugaan, Florence tiba-tiba memeluknya dan Mona hanya bisa terpaku—kaget.
“Nggak,” ucap Florence lirih, “Tadinya gue pikir lo emang keterlaluan. Lo yang bikin kita ketinggalan kereta. Tapi karena hal itu gue justru berterima kasih sama lo.”
Mona tercenung. Sesaat ia mengira dirinya telah salah dengar, “Berterima kasih?”
“Iya,” Florence melepaskan pelukannya dengan mata yang telah berkabut.
“Maksud lo?” Mona mengetuk-ketuk kepalanya sendiri dengan bingung. Ia merasa sebagian nyawanya masih tertinggal di alam mimpi.
“Gue bersyukur kemarin kita nggak jadi balik ke Jakarta.”
“Aduh, gue nggak ngerti deh,” erang Mona masih nggak nyambung juga kemana arah pembicaraan Florence, “Lo kesel banget ke gue karena gue pulang kesorean dan sekarang—”
“Mon,” Florence menatap sahabatnya lekat-lekat, gemetar, “Kereta itu—kereta yang seharusnya bawa kita pulang—mengalami kecelakaan.”
Mona membeku. Hatinya mencelos hingga ia tak bisa memahami apa yang diucapkan Florence.
“Hampir semua penumpang di kereta itu meninggal, Mon,” lanjut Florence dengan suara berat, “Gue nggak bisa ngebayangin kalo aja kemarin kita jadi pergi, mungkin juga kita ikut tewas dalam kecelakaan itu.”
Mona menggigil. Ia tidak tahu apakah harus senang ataukah sedih. Tapi sesuatu yang tajam mengusik kalbunya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan secara logika. Dennis mengajaknya ke pantai itu dan membuatnya lupa waktu. Mungkinkah ini cuma kebetulan semata? Kebetulan yang telah menyelamatkan nyawa Mona dan Florence. Entah kenapa Mona merasa ada black list dalam masa lalunya. Dan sosok Dennis yang amat misterius bagi Mona.
Selasa, 31 Maret 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)




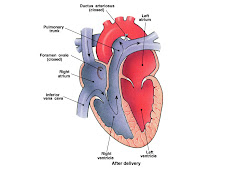











.jpg)
















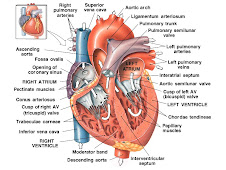






.jpg)













Tidak ada komentar:
Posting Komentar