MUDIK
6 0ktober 2007
Aku memegangi gada-gada bambu dari terpaan angin. Sementara ayah membantuku dengan tali temalinya dan kain putih seukuran 4 x 5 meter agar warung tenda kami dapat berdiri tegak. Tak urung kulihat keringat bercucuran dan raut letih di wajahnya yang kian keriput. Ada sedikit sesal menyusup dalam benak. Bukan karena aku tak bisa seperti teman-temanku dengan baju, sepatu dan segala sesuatu yang serba baru di Idul Fitri yang tinggal menghitung hari. Melainkan karena aku tak mampu berbuat lebih untuk menolong ekonomi keluargaku.
Sempat ada pikiran untuk putus sekolah. Maksudku baik, untuk mengurangi beban ortu tapi ayah justru memarahiku. Menurutnya, apapun yang terjadi aku harus menyelesaikan studiku minimal sampai di jenjang SMA. Ayah tak mau aku hidup susah seperti dirinya yang SD saja tak tamat. Dan setidaknya aku berusaha memahami keinginannya.
Seperti kata banyak orang, Ramadhan adalah bulan penuh berkah. Di sinilah aku dan keluargaku mengais rejeki tambahan. Mulai dari berjualan es kelapa muda sampai akhirnya kami mulai mendirikan tenda sejak H-7 menjelang lebaran. Tidak hanya kami yang melakukannya. Hingga sepanjang trotoar jalur pantura Brebes-Tegal tampak berjajar puluhan tenda yang menawarkan makanan maupun minuman. Bisa jadi itu sudah merupakan suatu tradisi dari tahun ke tahun dan dikenal dengan istilah warung tiban. Seperti halnya mudik yang tak dapat terlepas dari perayaan Idul Fitri.
***
10 Oktober 2007
Beberapa hari terakhir warung kami sepi. Nyaris tak ada pembeli meski seharusnya ini adalah puncak dari arus mudik. Aku tidak tahu, apa ini memang belum rejeki kami. Tapi kami tidak menyerah begitu saja. Masih ada dua hari sebelum lebaran. Setidaknya kami ingin mendapat sedikit uang untuk membeli sekilo ayam sebagai pendamping ketupat Sabtu nanti.
Tenda tetap kami dirikan. Aku bahkan rela menunggui warung ini dari pagi sampai malam bersama ayah dan adik laki-lakiku selama liburan sekolah. Untungnya adikku juga mengerti keadaan kami yang jauh dari berkecukupan dan dia tak banyak menuntut. Bukan hanya itu, kalaupun kali ini kami kurang beruntung, mungkin kami akan terus membuka warung tiban usai hari kemenangan. Siapa tahu arus balik akan mendatangkan rejeki bagi kami.
Senja telah datang. Meski langit mulai menebarkan bias jingga kemerahan, lalu lintas tak bisa dibilang lengang. Aku memperhatikan kendaraan satu persatu seraya berdoa dalam hati agar ada yang sudi mampir walau hanya untuk sepiring nasi. Namun yang kudapat hanya kepulan asap knalpot, hitam dan sesak.
Sayup-sayup adzan maghrib berkumandang. Aku melenguh setengah putus asa dan ayah tersenyum mencoba menyemangatiku sebelum ia dan adik akhirnya pamit pulang untuk sholat. Tak berapa lama kemudian terdengar deru motor melambat. Aku nyaris melompat kegirangan dan bergegas keluar, menyambut pembeli pertamaku hari itu.
“Sore, silakan mampir di tenda kami,” sapaku seramah mungkin.
Seorang lelaki muda yang sepertinya anak kuliahan turun dari motor bututnya yang super jelek, “Oh, tentu,” dia mendongak dan tampak mukanya berlepotan oleh debu tebal.
“Mari, Mas,” kataku lagi.
Pemuda itu mengikuti dan naik ke trotoar, duduk lesehan di atas tikar.
“Mau minum apa?”
Dan yang ditanya cuma garuk-garuk kepala, “Hari ini saya puasa,” gumamnya setelah berapa lama dan ia pun melanjutkan dengan nada malu, “Boleh saya minta segelas air untuk buka? Jujur, saya kehabisan ongkos dan sekarang saya tak ada uang sama sekali.”
Aku diam sebengong-bengongnya. Harapan untuk mendapatkan uang pupus sudah. Sekali pikiran jahat merasukiku, ‘Sial! Bukannya untung malah buntung’. Namun berikutnya terbersit rasa tak tega pada cowok itu. Setidaknya aku masih sedikit beruntung dan bisa buka puasa walau dengan lauk seadanya.
“Please?” pintanya memelas, “Segelas air putih juga nggak papa.”
Aku mematung. Iba itu kian berkecamuk dan tanpa sadar aku mengiyakan. Dengan perasaan aneh aku mengambil gelas dan mengisinya dengan teh dan es. Aku mengerling, mencuri-curi pandang. Pemuda itu meluruskan kakinya, setengah bersandar di tiang bambu. Matanya terpejam dalam desahan panjang. Terlihat ekspresi kelelahan yang terpancar jelas dari wajahnya. Entah kenapa kurasakan desir aneh yang tiba-tiba menggetarkan hatiku.
“Maaf, cuma ini yang bisa aku kasih. Es teh tanpa gula.”
“Makasih banyak ya. Ini udah lebih dari cukup,” ujarnya tersenyum lemah dan ia menenggak habis minumannya dalam hitungan detik seperti orang kehausan di padang pasir.
Aku melirik motor butut yang terparkir di luar. B, plat nomor Jakarta, “Mau mudik kemana nih?” tanyaku memecah keheningan.
“Jepara.”
Kemudian yang tertinggal hanya kebisuan yang amat janggal.
“Udah makan belum?”tanyaku dengan ketegangan yang sama. Cowok itu mendongak keheranan.
“Saya kan nggak punya uang.”
“Nggak papa. Lagian udah malam. Belum tentu juga nanti ada yang mau mampir ke sini.”
“Tapi—”
“Udah, anggap aja ini promosi. Siapa tau kamu bisa jadi penglaris warungku.”
“Bener nih?”
“Iya. Aku bakal berdosa banget biarin orang kelaparan setelah puasa seharian sementara di sini masih ada yang bisa dimakan.”
“Thanks,” pemuda itu mengangguk dan aku segera bangkit sebelum dilihatnya pipiku yang telah merona.
‘Setidaknya makanan ini takkan terbuang sia-sia. Begini lebih baik, kan jadi tidak mubadzir. Lagipula tidak ada salahnya bersedekah.’ batinku penuh kelegaan yang luar biasa.
“Sekali lagi makasih ya. Lain kali kalau kita ketemu, pasti semuanya aku bayar.”
Aku termenung. Mungkinkah akan ada lain kali? Dan hati kecil ini setengah berharap.
***
12 Oktober 2007
Bagi sebagian umat, ada yang meyakini 1 Syawal jatuh pada hari ini. Aku tidak mempermasalahkan hal itu. Namun bagi masyarakat awam sepertiku, mungkin aku akan ‘ngikut’ keputusan pemerintah. Dan sekarang ini giliran adikku dan ibu untuk jaga warung. Sementara aku membonceng sepeda ayah ke pasar demi membeli keperluan dagangan dan beberapa ikat sayur mayur untuk menu besok.
Mentari mulai naik sampai terik di puncak kepala. Udara di sekitarku seakan kian gersang akibat polusi yang meningkat karena arus mudik. Lalu lintas demikian sesak dan padat merayap. Ditambah masa prebegan dan adanya pasar tumpah di kawasan Bangjo (perempatan lampu abang ijo). Semua itu harus membuatku menahan nafas berat.
Mudik! Mudik! Mudik!
Brebes, kotaku yang jarang terjamah keramaian, mendadak populer karena terletak di jalur pantura. Brebesku yang adem ayem pun menjadi hiruk pikuk dan macet berkepanjangan sampai puluhan kilometer layaknya kota metropolitan. Aku tak tahu apakah harus senang ataukah susah dengan keadaan ini. Kemacetan yang hanya terjadi menjelang dan usai lebaran cukup membuat kepala pening. Tapi karena mudik ini aku bisa membantu ayah berjualan di pinggir jalan. Dan karena mudik juga, aku bertemu pemuda yang entah siapa namanya ...
***
13 Oktober 2007
Suka cita kusambut Idul Fitri meski dengan segala keterbatasan ekonomi. Aku tak peduli kalaupun harus merayakannya di rumah sederhana ini dengan ketupat dan sayur lodeh, tanpa opor ayam atau makanan mewah lainnya. Namun banyak hal yang bisa aku syukuri tahun ini. Puasaku selesai dan yang paling penting, aku dapat berkumpul dengan keluargaku, lengkap dalam keadaan sehat walafiat. Mau disadari atau tidak, Ramadhan kali ini aku melihat beberapa umat dipanggil oleh Yang Maha Kuasa dan tak bisa lagi bertemu hari besar ini, ada pula yang terbaring di rumah sakit, ada juga yang kecelakaan ketika akan ke kampung halaman. Kalau sudah begitu apa artinya baju dan sepatu baru? Tak lebih berharga dari keluarga yang utuh dan berbahagia.
***
14 Oktober 2007
Hari kedua aku kembali mendirikan tenda bersama ayah. Sepi! Jangankan ada pembeli, kota ini serasa mati …
***
15 Oktober 2007
Tidak seperti kemarin. Sekarang arus balik mulai ramai. Kendaraan dari timur ke arah Jakarta terlihat cukup berarti walau belum terlalu banyak. Munkin ada yang berusaha menghindari kemacetan pada puncak arus balik yang diperkirakan terjadi beberapa hari ke depan. Tapi apalah artinya nilai kuantitas karena tidak semua pemudik singgah di tenda ini.
Langit mendung dan angin sedikit bertiup. Aku duduk di trotoar, membisu dengan kesendirianku. Cukup bagiku menatap kendaraan yang berlalu lalang. Di belakang, ayah masih sibuk menyiapkan beberapa menu jikalau ada yang mau singgah.
Sesuatu membuyarkan lamunanku. Ku dengar deru mobil yang melambat dan sedan hitam itu berhenti tepat di depanku. Perlahan aku bangkit, menyambutnya dengan gembira. Bagiku pembeli berarti rejeki. Pintu mobil terbuka disusul sosok-sosok perlente dengan busana muslim yang terlihat mahal.
“Selamat siang. Mari silakan,” sapaku beramah tamah dan seorang laki-laki muda menghampiriku. Aku masih saja tertunduk, agak kaget. Biasanya hanya pengemudi sepeda motor yang menyempatkan diri untuk makan di warung kami.
“Ya,” kata laki-laki itu dengan anggukan kepala. Mata elangnya bersinar dan dia sungguh sangat tampan, membuatku tak punya nyali untuk menatapnya, “Saya Reno dan saya sengaja kemari untuk memenuhi janji saya tempo dulu.”
Janji?
Aku masih terpaku, tak tahu apa maksudnya sampai ayah tergopoh-gopoh datang menyongsong.
“Silakan duduk, mau pesan apa?” tanya ayah tiba-tiba.
Seorang lelaki paruh baya berdehem, “Begini, Pak—sebenarnya saya atas nama Reno, anak saya, ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya atas kebaikan putri bapak,” sambungnya.
Ayah langsung memandangku penuh tanda tanya, “Ehm maaf—jujur saya nggak ngerti,” gumamku sama bingungnya.
“Saya yang beberapa hari lalu minta air pada Mbak untuk buka puasa. Dan Mbak juga menawari saya makan.”
Aku terhenyak. Segala sesuatu mendadak berputar di otakku layaknya gangsing.
Jadi pemuda dekil dengan motor butut yang waktu itu ternyata anak gedongan. Pikirku nyaris tak percaya. Kok bisa?
Aku menengadah, mencoba melihatnya lebih jelas. Memang benar! Dia mirip sekali dengan cowok itu. Cowok yang sempat membuatku berbunga-bunga. Dia cowok yang sama dengan pemuda kumal yang kelelahan dalam perjalanan mudik hingga berhenti di tendaku. Dan aku kembali merasakan gejolak aneh yang tak bisa kujelaskan.
“Bukan cuma itu, Reno juga bilang kalau masakan di sini enak sekali,” ungkap wanita berjilbab yang kelihatan lebih muda dari umur sebenarnya.
“Rencananya bulan depan Papa saya akan membuka Café di salah satu Mall di Tegal,” lanjut Reno, “Kami benar-benar membutuhkan koki yang handal. Dan saya percaya pada Bapak dan putri bapak. Itu juga kalau Bapak sekeluarga tidak keberatan.”
Jadi koki? Di Café?
Aku dan ayah saling berpandangan.
“Ten—tentu! Saya bersedia dan keluarga saya juga pasti nggak akan keberatan,” seru ayah bersemangat.
Reno dan orang tuanya tersenyum lega sementara aku belum bisa berkata-kata. Apa yang terjadi beberapa menit terakhir merupakan kejutan luar biasa yang sulit ku cerna.
“Lagipula saya yakin, Bapak akan bisa memenuhi selera masyarakat kota ini,” kata Papa Reno lagi.
“Sa—saya nggak tahu gimana membalas anugerah ini,” ucapku tergagap masih dengan mengheningkan cipta, “Tapi saya sungguh sangat berterima kasih.”
Reno tersenyum lebar dan menjabat tanganku. Sentuhan kecil itu menimbulkan ledakan luar biasa di relung hatiku. Tanpa sadar air mata bahagia menghalangi pandanganku. Mimpi apa aku semalam? Dapat rejeki sebesar ini. Bekerja di tempat elit seperti Café? Membayangkannya pun aku tak pernah. Dan kurasa kerja sama kecil ini akan lebih sering mempertemukanku dengan Reno. Tapi pantaskah aku mencintainya? Seperti pungguk yang merindukan bulan …




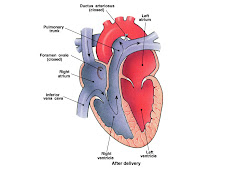











.jpg)
















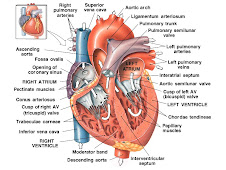






.jpg)













Tidak ada komentar:
Posting Komentar